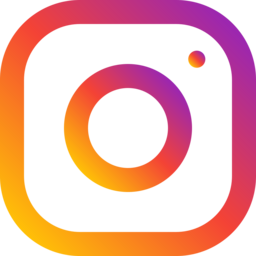Belajar dari Sawah dan Petani Bali
 Editor |
08 Juli 2023 | 09:03:00 WITA
Editor |
08 Juli 2023 | 09:03:00 WITA

JIKA pandangan homo faber meyakini kerja membuat kualitas manusia menjadi berbeda dari binatang, dan melalui kerjalah manusia sejatinya sedang memanusiakan alam, rasa-rasanya tak berlebihan bila dikatakan visi homo faber itu nyata telah mengejawantah dalam proses kerja masyarakat petani di Bali. Desa Jatiluwih, terletak di daerah Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan air laut, kawasan ini menawarkan kesejukan dan juga terkenal memiliki panorama persawahan yang indah. Berada di kaki Gunung Batukaru yang tampak anggun, beranjangsana ke Jatiluwih laksana berdiri di depan kanvas sebuah lukisan Mooi Indie. Gunung-gemunung bersanding halimun, sejauh mata memandang, hamparan padi hijau menguning, nyiur melambai berjajar-jajar, dan sungai mengalir jernih membelah sawah-sawahnya. Semuanya terlihat membentuk lanskap budaya nan asri. Ya, jika pandangan homo faber meyakini kerja membuat kualitas manusia menjadi berbeda dari binatang, dan melalui kerjalah manusia sejatinya sedang memanusiakan alam, rasa-rasanya tak berlebihan bila dikatakan visi itu telah mengejawantah dalam masyarakat petani di Bali. Bagaimana tidak, masyarakat petani bukan sekadar mengolah tanah dan air untuk memenuhi kebutuhannya, mereka juga tengah bekerja memanusiawikan alam dan lingkungannya. Pembuatan sengkedan atau terasiring, selain bermanfaat menambah stabilitas lereng, mencegah banjir dan longsor, memudahkan pengolahan tanah, memperkecil kemiringan lereng, juga berfungsi memperpanjang daerah resapan air. Lebih dari itu, laiknya proses kreatif seorang seniman, mereka bekerja seolah tengah mengukir dan memperindah dunia, pembuatan terasiring menciptakan pemandangan mempesona. Bentangan alam dengan komposisi gunung-gemunung, yang di atasnya diubah jadi persawahan bertingkat-tingkat, aliran sungai berkelok-kelok membelah sawah-sawah, plus lembayung senja jelang mentari tenggelam di ufuk barat, jelas menciptakan keindahan panorama laiknya lukisan seniman naturalis. Ya, demikianlah sebuah lanskap budaya terwujud, dibentuk dari perpaduan antara kerja alam dan kerja manusia. Benar, persawahan terasiring jelas bukanlah monopoli Bali-Indonesia. Fenomena ini lazim ditemui di kawasan Asia. Sebutlah di Filipina, Vietnam, Thailand, atau Cina, misalnya, di sana juga ditemui model pengolahan persawahan terasiring. Namun bicara sistem Subak, barangkali merupakan kekhasan budaya masyarakat petani di Bali dan satu-satunya di dunia. Tak aneh, bicara tren kunjungan wisatawan di Desa Jatiluwih, salah satunya untuk melihat panorama persawahan di sana, cenderung naik. Terlebih sejak UNESCO menetapkan sistem Subak di Bali sebagai situs warisan budaya dunia. Sebutlah tahun 2014, misalnya, tercatat jumlah kunjungan wisatawan asing maupun domestik ke Desa Jatiluwih mencapai sekitar 165.144. Meskipun sempat turun pada 2015 menjadi 164.366, di tahun-tahun selanjutnya kedatangan wisatawan asing maupun domestik memperlihatkan tren kenaikan. Yakni, pada 2016 sebanyak 213.509, pada 2017, 250.973 orang, dan pada 2018, sebesar 277.189. Bicara popularitas sistem Subak naga-naganya kini bahkan telah mendunia. Ini terlihat dari momen kedatangan mantan Presiden Amerika Serikat ke-44. Minggu, 25 Juni 2017, Barack Obama dan keluarga saat tengah berlibur di Pulau Dewata sempat meluangkan diri singgah ke Desa Jatiluwih. Mereka berjalan kaki menyusuri persawahan sejauh setengah kilometer, bahkan hingga mencapai salah satu teras sawah yang termasuk kawasan Catur Angga Batukaru. Pertanyaannya ialah, apakah yang membuat sistem persawahan masyarakat petani Bali jadi popular mendunia? Apakah pelajaran dan pengalaman berharga yang bakal didapatkan saat kita bertandang ke sana, dan menyimak aspek tak bendawi (intangible) terkait sebuah objek berupa persawahan bertingkat-tingkat dan sistem Subak di sana? Outstanding Universal Value Proses pengusulan Subak ini jelas bukanlah perkara mudah. Selain diperlukan penelitian mendalam, juga dibutuhkan pendekatan multidisipliner. Seperti arkeologi, antropologi, arsitektur lanskap, geografi, ilmu lingkungan, dan lainnya. Praktis setelah diperjuangkan selama 12 tahun barulah dalam sidang ke-36 Komite Warisan Dunia UNESCO di kota Saint Peterburg, Rusia, akhirnya pengusulan Subak sebagai warisan budaya dunia ini disetujui dan telah ditetapkan pada 29 Juni 2012. Subak di Bali yang mendapatkan penetapan UNESCO memiliki luas areal sekitar 19.500 hektar. Ini terdiri dari empat kawasan. Pertama, Lanskap Subak Catur Angga Batukaru, di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng. Kedua, Pura Taman Ayun, di Kabupaten Badung. Ketiga, Lanskap Subak Daerah Aliran Sungai Pakerisan, di Kabupaten Gianyar. Dan keempat, Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur, di Kabupaten Bangli. Menyimak situs UNESCO https://whc.unesco.or, sistem Subak di Bali ini diberi judul “Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy”. Dari judul itu tampak jelas, aspek filosofis yaitu Tri Hita Karana jadi bobot utama pengakuan dan penetapan oleh UNESCO. Akan tetapi jikalau disimak lebih dalam, poin substansi lain juga segera mengemuka. Selain aspek filosofis, UNESCO mencatat aspek historis dan semesta tata nilai-nilai seperti praktik egalitarian dan demokratis dalam proses pengelolaan sistem irigasi tersebut. Tak salah, jikalau dilihat secara utuh, segera muncul hikmah berharga dari sebuah khasanah local wisdom, yang bukan saja unik melainkan juga memiliki nilai-nilai universal yang kuat. Mari kita simak, satu demi satu. Sejarah Merujuk buku Tugas-tugas Parajuru Subak yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, disebutkan Subak telah ada di Bali sejak 882 M. Dalam Prasasti Sukawana terdapat kata ‘huma’ yang berarti sawah dan ‘parlak’ yang berarti tegalan atau ladang. Prasasti Bebetin dibuat 896 M juga memuat hal serupa. Inskripsi ini mencantumkan istilah ‘undagi pengarung’, yang artinya ialah tukang membuat terowongan air. Masih dari kisaran abad ke-9, dalam Prasasti Turunyan ditemui kata “ser-danu” yang diduga berarti Kapala Urusan air danau. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ‘ser’ inilah kemudian menjadi pekaseh, yaitu orang yang bertugas mengatur air dalam sistem Subak. Sedangkan dari abad ke 11, Prasasti Batuan yang dibuat pada 1023 M telah disebut kata ‘sawah’. Kata ‘sawah’ juga tercantum pada Prasasti Tengkulak yang dibuat 1023 M, yaitu masa kekuasaan Sri Dharma Wangsa (1022 -1048) memerintah Bali. Di masa ini diduga sistem pengairan telah diatur dengan baik berdasarkan asas kebersamaan dan keadilan. Pun bisa disimak Prasasti Pandak Badung, 1072 M. Kata subak berasal dari kata ‘suwak’, sedangkan wilayah Subak sendiri di masa lalu disebut ‘kasuwakan’. Dalam Prasasti Badung ini, untuk pertama kalinya muncul kata ‘kasuwakan’. Istilah ini pada perkembangannya kemudian berubah pelafalan jadi ‘kasubakan’ atau ‘subak’. Sementara itu, UNESCO mendalilkan, sistem Subak di Bali ini berasal dari abad ke-10. Lanskap Subak Catur Angga Batukaru yang berlokasi di Desa Jatiluwih, yang pernah dikunjungi mantan Presiden AS itu, seturut pendapat UNESCO telah disebutkan dalam sebuah inskripsi prasasti yang berasal dari era tersebut. Sistem Filsafat Bicara sistem Subak di Bali, merujuk Sang Putu Kaler Surata dalam karyanya Ekopedagogi (2015), memiliki paling tidak empat ciri, yaitu: pertama, lahan sawah dengan batas yang pasti; kedua, bangunan irigasi untuk mengalirkan air ke persawahan; ketiga, organisasi krama (anggota) Subak dengan keanggotaan bersifat tetap; dan keempat terdapat rangkaian pura dan pelinggih (water temple) baik untuk ritual keagamaan maupun pertemuan anggota. Menariknya, keempat elemen pembentuk sistem Subak ini dipayungi oleh sebuah pandangan-dunia (world of view) atau sistem filsafat yang dikenal dengan nama Tri Hita Karana. Tri Hita Karana merupakan ajaran filosofi Hindu yang selalu ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat adat di Bali, termasuk di sini pada sistem Subak. Berasal dari kata ‘tri’ yang berarti tiga, ‘hita’ artinya kebahagiaan, dan ‘karana’ berarti penyebab. Dengan begitu Tri Hita Karana berarti “Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan”. Makna konsepsi itu ialah pengertian tiga penyebab kesejahteraan bersumber pada keharmonisan hubungan ketuhanan (parahyangan), kemanusian (pawongan), dan kesadaran ekologis dalam mengelola alam (palemahan). Ketiga prinsip ini harus senantiasa diimplementasikan secara seimbang sehingga tercipta keharmonisan sejati. Menurut UNESCO, nilai-nilai Tri Hita Karana tercermin kuat dalam sistem Subak. Menariknya, UNESCO juga melihat Tri Hita Karana sejatinya bukan hanya bersifat partikular atau lokalistik Bali-Indonesia belaka, melainkan juga merupakan pengejawantahan nilai-nilai universal yang luar biasa (universal outstanding values). Semesta Nilai-nilai Masyarakat petani Bali berpandangan air ialah karunia Dewi Danu, yaitu Tuhan dalam manifestasi-Nya sebagai pelindung danau atau air (tirtha). Pura air utama yaitu Pura Ulun Danu, menjadi lokus pelinggih bagi Dewi Danu. Karena keperluan praktis dan didorong keyakinan spiritual yang kuat, masyarakat petani Bali sengaja mengembangkan model jejaring kerja Pura Subak sebagai basis dari sistem irigasi mereka. Air dialirkan melalui berbagai rangkaian pura-pura. Pura Ulun Danu berada di posisi hirarkis tertinggi. Ia memiliki rangkaian pura-pura di bawahnya, yakni puluhan pura di tingkatan DAS, ratusan pura pada tingkatan Subak, dan ribuan pura pada tingkatan sawah petani. Hasilnya ialah membentuk sistem irigasi berbasis jejaring antar pura air (water temple). Antropolog John Stephen Lansing (1991) dalam karyanya Priest and Programer memaparkan perihal alasan petani di sebelah hulu bersedia berbagi air dengan petani di hilir. Menurutnya, jika air irigasi hanya dimanfaatkan masyarakat petani di hulu, maka petani di hilir karena kekurangan air bisa dipastikan tidak bisa menanam padi. Ini ternyata justru menyebabkan hama dan penyakit tanaman berpotensi besar menyerang persawahan di hulu dengan konsekuensi gagal panen. Sebaliknya, jika dilakukan koordinasi dan berbagi air, sehingga masyarakat di bawahnya hingga di hilir bisa memperoleh air dan menanam padi, ternyata potensi serangan hama dan penyakit tanaman justru lebih bisa dikendalikan. Mengapa demikian? Menurutnya, kata kunci di balik keberhasilan ini justru karena populasi hama dan penyakit tanaman akan menyebar pada kawasan yang lebih luas dan tidak terkonsentrasi pada satu lokasi tertentu saja. Lansing juga memaparkan, jika terjadi sengketa antara dua Subak dalam pengelolaan air irigasi, kedua Subak itu diharapkan bisa bermusyawarah untuk mencari pemecahan terhadap sengketa mereka. Namun jika gagal, musyawarah dilakukan pada tingkat DAS. Jika masih tetap gagal, musyawarah berpuncak dilakukan pada tingkat Pura Ulun Danu. Pula soal penentuan musim tanam, pola panen, dan mekanisme pengendalian hama atau penyakit tanaman, semua itu selalu diputuskan secara bersama dan berhati-hati guna memperoleh panen padi yang maksimal. Menariknya, kegiatan pertemuan untuk bermusyawarah ini selalu diawali dengan ritual bersama kepada Dewi Danu. Tak salah UNESCO pun mencatat, sistem Subak sebagai praktik pertanian di Bali bersifat demokratis dan egaliter. Ya, sistem Subak dikatakan demokratis dan egalitarian karena setiap kebijakan—baik terkait ritual, pengelolaan air, pola panen, tata guna lahan, dan lain sebagainya—semuanya diputuskan berdasarkan kesepakatan semua anggota Subak. Adanya prinsip tata kelola yang baik atau popular dengan istilah “good governance” ini, rasa-rasanya juga merupakan alasan kuat, UNESCO mengakui dan menetapkan sistem subak di Bali sebagai warisan budaya dunia. (riki/sut)








.jpeg)