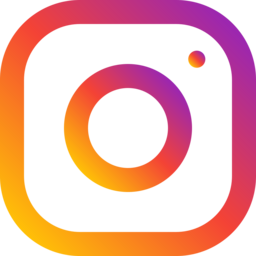Sampah yang Tak Diakui
 Editor |
17 April 2025 | 21:25:00 WITA
Editor |
17 April 2025 | 21:25:00 WITA

DI SIMPANG Tohpati, empat tubuh ringkih terjaring razia. Mereka disebut "Gepeng" – akronim dingin untuk Gelandangan dan Pengemis. Satuan Polisi Pamong Praja bertindak, merujuk pada lembaran peraturan daerah tentang ketertiban umum. Kepala Satpol PP bicara tentang pembinaan, pengarahan, dan imbauan agar masyarakat tak lagi menyalurkan receh pada uluran tangan yang kosong. Kota Denpasar, katanya, harus tertib dan aman. Namun, di balik retorika ketertiban itu, tersembunyi wajah lain. Wajah sebuah kegagalan yang enggan diakui. Empat sosok yang terjaring di lampu merah itu bukanlah sekadar anomali yang mengganggu estetika kota. Mereka adalah cermin buram dari ketidakmampuan sebuah sistem untuk merawat warganya. Mereka adalah residu dari janji-janji pembangunan yang tak pernah sepenuhnya sampai pada lapisan paling bawah. Mengapa mereka ada di sana, di tengah deru kendaraan dan tatapan acuh pengendara? Bukankah itu pertanyaan yang lebih mendasar ketimbang sekadar menggiring mereka ke pinggiran, menjauh dari pandangan mata yang risih? Mereka adalah "sampah" yang tak pernah kita akui sebagai produk sampingan dari ketidakadilan, dari jurang menganga antara kemewahan dan kemiskinan. Sampah yang kita buang, lalu pura-pura lupa dari mana asalnya. Ironisnya, imbauan untuk tidak memberi justru mengisyaratkan menipisnya rasa peduli. Dulu, mungkin ada sebentuk iba, sebuah dorongan spontan untuk meringankan beban sesaat. Kini, yang didorong adalah kepatuhan pada aturan, sebuah sterilisasi ruang publik dari pemandangan yang dianggap "mengganggu". Ketidakpedulian menjelma menjadi kebijakan, rasa iba digantikan oleh perintah untuk menjauhkan diri. Pembinaan dan pengarahan macam apa yang bisa mengubah akar persoalan? Bisakah selembar nasihat menghapus luka kemiskinan yang mungkin telah menggerogoti hidup mereka sejak lama? Sanksi pembinaan, kata mereka. Seolah-olah kemiskinan adalah sebuah pelanggaran yang bisa disembuhkan dengan ceramah singkat. Kota yang tertib dan aman memang dambaan. Namun, ketertiban yang dibangun di atas pengabaian dan keamanan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang adalah ketertiban dan keamanan yang rapuh. Ia hanya menunda masalah, menggesernya ke sudut-sudut yang tak terlihat, hingga suatu saat ia akan kembali menganga. Mungkin, alih-alih sibuk menjaring "gepeng", pemerintah perlu bercermin lebih dalam. Melihat wajah kegagalannya sendiri dalam tatapan kosong mereka. Masyarakat pun perlu merenung, apakah ketidakpedulian yang semakin membudaya ini adalah harga yang pantas dibayar untuk sebuah kota yang katanya "nyaman". Sebab, sampah yang tak diakui akan terus bergentayangan, menjadi hantu bagi nurani yang perlahan mati. Di simpang Tohpati, hari ini, empat cerita pilu kembali dipinggirkan. Besok, mungkin akan ada lebih banyak lagi. Dan kita akan terus berpura-pura bahwa mereka hanyalah gangguan ketertiban. (*) (Argus Darshan)
Baca juga:
Bebal