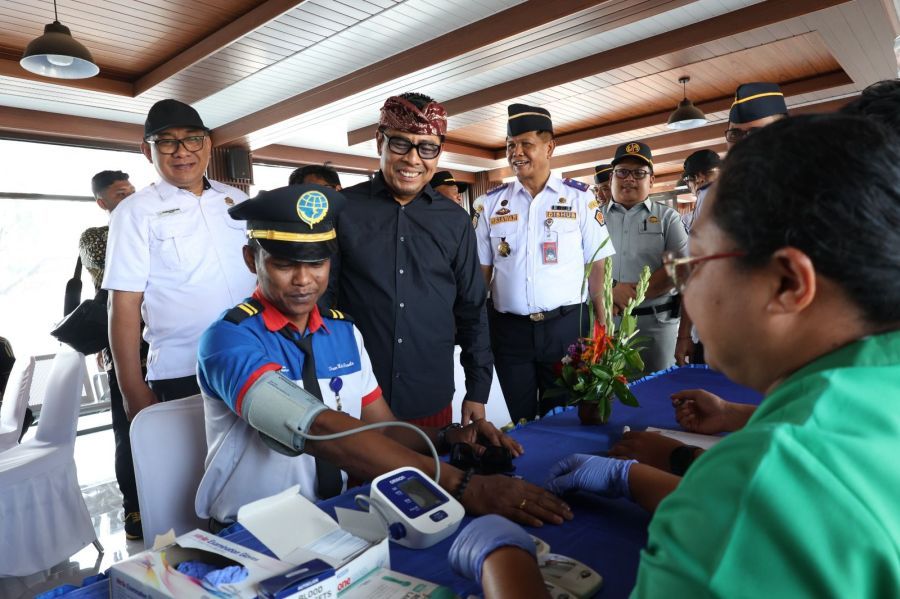Pakar Serukan Etika Tinggi bagi Pejabat dalam Komunikasi Publik

YOGYAKARTA, PODIUMNEWS.com - Komunikasi publik menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo–Gibran menjelang satu tahun masa kepemimpinannya. Sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah pernyataan pejabat negara kerap menimbulkan kontroversi di ruang publik. Gaya berkomunikasi yang reaktif dan tidak sensitif terhadap kritik dinilai memunculkan jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Fenomena ini mendapat perhatian dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam Diskusi Komunikasi Magister (Diskoma) Fisipol UGM edisi ke-24 bertajuk “Dari Retorika Arogansi Menuju Retorika Urgensi”, Kamis (25/9/2025), pakar komunikasi publik Prof Nyarwi Ahmad PhD, menilai bahwa akar krisis komunikasi pejabat terletak pada kegagalan memahami perbedaan antara persuasi dan pemaksaan.
“Jadi coercion (pemaksaan) berbeda dengan persuasi,” ujar Nyarwi. Ia menjelaskan bahwa persuasi sejatinya merupakan proses dialogis yang didukung data dan rasionalitas, dilakukan untuk mengubah sikap publik melalui argumentasi yang logis dan saling menghormati. Sebaliknya, komunikasi yang memaksa justru memperlihatkan sikap defensif dan cenderung menutup ruang diskusi.
Nyarwi menilai pernyataan pejabat yang reaktif terhadap kritik publik menjadi cermin dari kegagalan membangun persuasi yang sehat. Ia mencontohkan pernyataan seorang menteri yang merespons kritik dengan kalimat “kabur ajalah, kalau bisa tidak usah kembali.” Bagi Nyarwi, gaya komunikasi seperti itu memperlihatkan ketidaksiapan menghadapi perbedaan pendapat. “Ini menunjukkan bukan solusi dan diskusi yang ditawarkan, melainkan arogansi,” jelasnya.
Pandangan serupa disampaikan praktisi komunikasi Dr Agus Sudibyo. Menurutnya, kaburnya batas antara ruang privat dan ruang publik di media sosial menjadi salah satu sumber persoalan. Banyak pejabat, katanya, tidak menyadari bahwa media sosial yang mereka gunakan bukan lagi wadah pribadi, melainkan panggung komunikasi massa yang dapat membentuk persepsi publik secara luas.
“Dengan standar etika yang kabur, maka pejabat harus menggunakan etika tertinggi untuk komunikasi massa yang mensterilkan dari apriori, insinuasi, intimidasi, dan ujaran kebencian,” kata Agus. Ia mengingatkan bahwa setiap pernyataan pejabat di ruang digital memiliki bobot politik dan moral yang jauh lebih besar dibandingkan warga biasa, sehingga perlu disampaikan dengan tanggung jawab penuh.
Para akademisi menekankan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan tekanan politik, pejabat negara harus lebih berhati-hati dalam berbahasa. Etika komunikasi publik bukan hanya soal tata krama, tetapi juga bagian dari tanggung jawab kekuasaan dalam menjaga kepercayaan publik. Ketika pejabat kehilangan kendali dalam tutur kata, kredibilitas pemerintahan ikut tergerus.
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya membangun komunikasi publik yang beradab, transparan, dan berorientasi pada dialog. Pemerintah diharapkan mulai menempatkan komunikasi sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, bukan sebagai alat pembenaran diri.
(riki/sukadana)