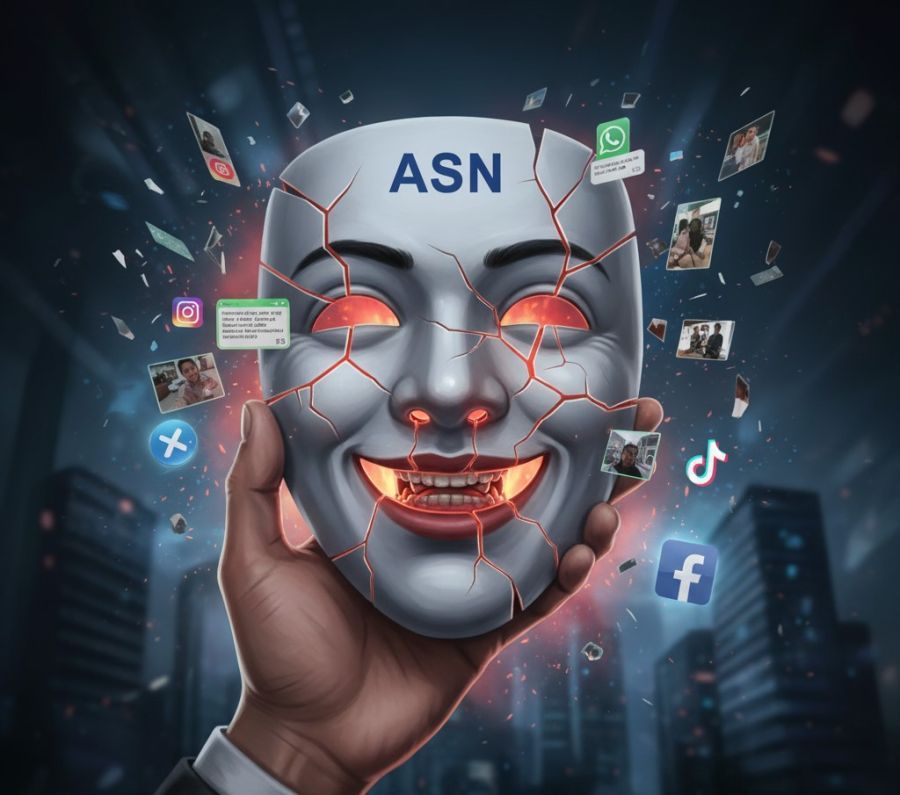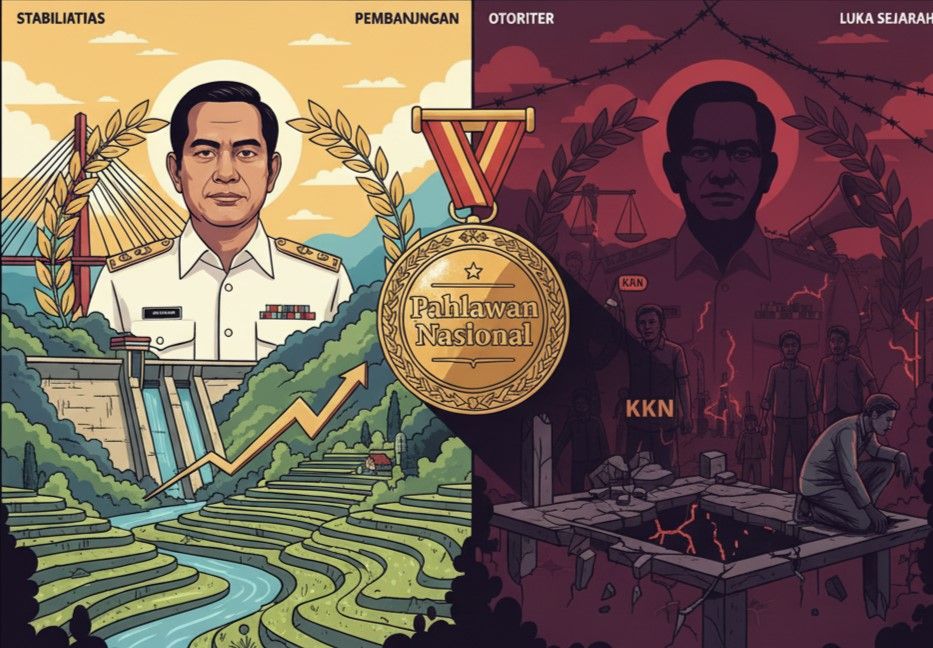Rupiah Pintu Gerbang dan Neraca Keberlanjutan

PEREKONOMIAN Bali adalah sebuah mahakarya yang dibangun di atas fondasi tunggal: pariwisata. Dengan kontribusi sektor ini yang melampaui 40 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan Bali, yang diproyeksikan di atas 5 persen pada tahun 2024, memang solid, tetapi rentan. Ketergantungan struktural ini, yang oleh ekonom sering disebut sebagai single engine economy, menciptakan dilema etis dan fiskal yang mendesak: bagaimana memastikan mesin ekonomi ini tidak menghancurkan rumah yang menopangnya, yaitu lingkungan dan budaya.
Untuk menjawab dilema ini, Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan Pungutan Wisatawan Asing (The Bali Tourism Levy) sebesar Rp150.000 sejak Februari 2024. Pungutan ini bukan pajak, melainkan biaya yang secara eksplisit dialokasikan untuk pelindungan kebudayaan dan pemulihan lingkungan alam Bali. Konsepnya adalah "Beban Sang Dewi," di mana mereka yang menikmati kekayaan Bali turut membayar biaya konservasi. Namun, analisis kritis menunjukkan bahwa instrumen fiskal yang strategis ini sedang diuji efektivitas, governance, dan daya tahannya.
Ekspektasi dan Defisit Realisasi
Di atas kertas, potensi pendapatan dari pungutan ini sangat menjanjikan. Dengan tren kunjungan wisatawan mancanegara yang kembali normal (mencapai sekitar 450.000 kunjungan per bulan), total penerimaan tahunan diproyeksikan dapat menyentuh angka ambisius, yakni Rp1 triliun.
Dana sebesar ini, jika dikelola secara efisien, akan menjadi suntikan modal vital untuk mengatasi masalah kronis Bali, dari tumpukan sampah plastik hingga perbaikan infrastruktur irigasi Subak yang ambruk, yang merupakan warisan dunia.
Namun, data realisasi di lapangan menunjukkan adanya defisit signifikan. Hingga September 2024, dana yang berhasil terkumpul baru berada di kisaran Rp211,8 miliar. Kepala Dinas Pariwisata Bali mengakui bahwa hanya sekitar 40 persen dari total turis asing yang menunaikan kewajiban ini.
Rendahnya tingkat kepatuhan 60 persen wisatawan yang belum membayar adalah indikasi perlunya perbaikan mendasar dalam mekanisme penagihan dan pengawasan. Meskipun sebagian besar pembayaran (80 persen hingga 90 persen) dilakukan secara digital sebelum kedatangan, sisa yang belum terbayar menunjukkan beberapa masalah kritis.
Salah satu kendala utama adalah teknis fungsionalitas. Keterbatasan infrastruktur fisik, terutama ketiadaan auto scanner gate yang terintegrasi di bandara, membuat penegakan hukum di pintu masuk menjadi longgar dan mengandalkan pengawasan manual. Hal ini sangat tidak optimal untuk volume wisatawan yang masif.
Masalah lain adalah sosialisasi dan kesadaran. Sebagian besar wisatawan asing mungkin masih menganggap pungutan ini sebagai biaya opsional atau belum sepenuhnya memahami urgensi dan tujuannya. Kepatuhan yang rendah ini berujung pada hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya menjadi modal lingkungan.
Oleh karena itu, kegagalan mencapai target optimal menunjukkan keharusan untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang menaungi pungutan ini. Revisi harus mencakup skema sanksi atau disinsentif yang jelas dan tegas bagi wisatawan yang terbukti mengabaikan kewajiban, bukan hanya imbauan.
Tekanan Fiskal Beban Ganda Industri
Pungutan ini tidak berdiri sendiri dalam lanskap fiskal Bali. Industri pariwisata dan sektor properti kini menghadapi akumulasi tekanan fiskal yang berpotensi memengaruhi iklim investasi jangka panjang.
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen di tingkat nasional, ditambah dengan kenaikan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) yang signifikan pada aset properti komersial, telah menambah biaya operasional dan biaya kepemilikan aset. Bagi investor, fiscal stacking ini akan memengaruhi perhitungan break-even point dan minat mereka menanamkan modal di Bali, khususnya di sektor akomodasi.
Dari perspektif keberlanjutan, penambahan biaya (baik pajak maupun pungutan) harus diimbangi oleh dua faktor krusial. Faktor pertama adalah Nilai Tambah Infrastruktur; setiap beban fiskal harus diterjemahkan menjadi perbaikan kualitas nyata, misalnya jalan yang lebih bersih, manajemen sampah yang modern, atau air yang terjamin, sehingga wisatawan merasa pungutan tersebut sepadan.
Faktor kedua adalah Keadilan Fiskal (Fiscal Equity). Jika beban pariwisata terus ditingkatkan, pemerintah harus memastikan ada insentif lain, seperti kemudahan birokrasi, yang diberikan kepada investasi di sektor non-pariwisata, seperti pertanian atau ekonomi digital, untuk mendorong diversifikasi dan mengurangi risiko single engine economy.
Para pelaku bisnis pariwisata sangat mengkhawatirkan bahwa akumulasi beban fiskal ini dapat menggerus daya saing global Bali, membuat destinasi lain dengan beban fiskal yang lebih ringan menjadi pilihan bagi wisatawan yang sensitif harga.
Uji Transparansi dan Kontrak Sosial
Tujuan inti pungutan ini adalah sebagai instrumen paralelisme fiskal, di mana industri yang paling diuntungkan dari alam Bali juga menjadi kontributor utama pemeliharaan alam tersebut. Ini adalah pembaharuan dari kontrak sosial antara pemerintah, wisatawan, dan lingkungan.
Keberhasilan jangka panjang pungutan ini bergantung sepenuhnya pada transparansi dan akuntabilitas alokasi dana. Dengan dana yang telah terkumpul (Rp211,8 miliar), publik dan industri berhak menuntut detail rencana induk (master plan) penggunaan dana tersebut.
Analisis harus secara spesifik mencakup peta jalan pengelolaan sampah, yaitu berapa alokasi untuk teknologi waste-to-energy atau TPA regional. Selain itu, prioritas lingkungan juga harus jelas, yaitu berapa dana yang dialirkan untuk perbaikan infrastruktur Subak (sebagai Warisan Budaya Dunia) dan proyek konservasi biodiversity.
Jika dana ini justru dimasukkan ke kas umum atau dialokasikan untuk proyek yang tidak berkaitan dengan pelestarian dan lingkungan, kepercayaan publik dan industri pariwisata akan runtuh. Pungutan ini akan dipersepsikan sebagai beban administratif yang tidak efektif, bahkan kontraproduktif.
Analisis Institusi dan Tanggung Jawab Global
Para ekonom seperti Daron Acemoglu dan James Robinson dalam "Why Nations Fail" mungkin akan melihat kebijakan ini sebagai upaya membangun institusi yang lebih inklusif, mencoba mengalihkan institusi ekstraktif (yang hanya menguntungkan segelintir pihak dari pariwisata) menjadi yang lebih adil dan berkelanjutan. Namun, jika pungutan ini tidak transparan dan dananya bocor, ia hanya akan menjadi institusi ekstraktif baru yang membebani tanpa memberikan manfaat riil.
Dari perspektif etika, Peter Singer dalam karyanya "Famine, Affluence, and Morality" akan berargumen bahwa negara-negara maju dan individu-individu yang berwisata memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada pemeliharaan ekosistem yang mereka nikmati, terutama jika mereka mampu. Pungutan ini adalah manifestasi dari prinsip itu, namun efektivitasnya bergantung pada akuntabilitas.
Kesimpulan Modal Diversifikasi Risiko
Pungutan wisatawan asing adalah sebuah inovasi fiskal yang menjanjikan untuk membangun ketahanan ekonomi dan ekologis Bali. Namun, instrumen ini adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah modal penting untuk perbaikan kualitas dan diversifikasi risiko dari ketergantungan pariwisata. Di sisi lain, kegagalan dalam governance (penagihan yang suboptimal) dan transparansi (alokasi dana yang tidak jelas) akan merusak kredibilitas kebijakan ini.
Untuk mewujudkan potensi Rp1 triliun dan memastikan keberlanjutan Bali, diperlukan ketegasan politik dalam mengakselerasi solusi teknis (seperti pengadaan auto scanner) dan komitmen moral untuk menjadikan dana ini sebagai modal green economy yang terpisah dari belanja rutin daerah. Hanya dengan demikian, beban Rupiah di Pintu Gerbang ini dapat benar-benar menjadi strategi seimbang bagi masa depan Bali. (*)
Menot Sukadana