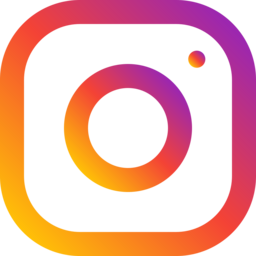Mengapa Coffee Shop Tak Menjual Kopi Bali?
 Editor |
19 Mei 2025 | 18:49:00 WITA
Editor |
19 Mei 2025 | 18:49:00 WITA

SORE itu, langit Denpasar menggantung kelabu. Saya bertemu dua kawan lama di sebuah coffee shop di Teuku Umar Barat. Seorang pengacara, satu lagi pengusaha wanita, keduanya saya kenal sejak masa-masa larut diskusi di kantin kampus. Kini, jalan hidup membawa kami ke ranah berbeda, tapi semangatnya masih serupa: mencintai yang lokal, merawat yang dekat. Sudah jadi kebiasaan, setiap kali bertemu di kedai kopi, saya tak repot membuka menu. "Pesan kopi Bali, ya," kata saya, mantap. Namun, pelayan muda yang ramah itu menggeleng pelan. “Kami tidak menyediakan kopi Bali, Pak. Tapi kalau mau yang hitam, bisa pesan Americano.” Saya mengangguk. Tidak banyak pilihan. Ironis. Di tanah Bali, di jantung Denpasar, saya harus menyeruput Americano karena kopi Bali tak tersedia. Padahal, pertemuan kami hari itu bukan sekadar temu kangen. Kami sedang membahas peluang kolaborasi untuk mendorong UMKM lokal. Teman saya kini memimpin komunitas perempuan pelaku UMKM. Ia bercerita tentang upayanya membantu kopi Banyuatis—kopi dari lereng utara pulau ini—menembus pasar oleh-oleh. “Kita khawatir, anak-anak muda yang biasa nongkrong di coffee shop seperti ini lama-lama akan terbiasa dengan kopi berlidah bule. Kalau itu terjadi, kopi lokal akan ditinggalkan,” katanya. Kami diam sejenak. Kalimat itu menggantung. Saya teringat rasa kopi Banyuatis—earthy, pahit bersih, dengan asam tipis di ujung lidah. Teman larut malam kami semasa kuliah. Rasa yang mungkin tak “instagenik”, tapi menyimpan aroma tanah, kampung, dan kerja keras petani. Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi kopi Bali menurun dari 7.100 ton pada 2017 menjadi sekitar 5.600 ton di 2022. Sementara itu, konsumsi kopi terus naik, terutama di kalangan anak muda yang menjadikan coffee shop sebagai rumah ketiga mereka. Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, MT, akademisi Universitas Udayana yang fokus pada pengembangan kopi lokal, pernah mengatakan bahwa dominasi selera pasar bukan semata soal rasa, tapi konstruksi gaya hidup. Ketika kopi lokal dianggap kurang keren, perlahan ia akan hilang dari lidah. Saya menyetujui kegelisahan itu. Bukankah selama ini kita ramai menggaungkan cinta produk lokal? Pemerintah daerah pun telah mengeluarkan seruan untuk memakai hasil pertanian Bali di hotel, restoran, dan toko oleh-oleh. Tapi mengapa coffee shop—ikon gaya hidup urban—malah luput dari gerakan ini? Mungkin karena kopi lokal dianggap terlalu sederhana. Mungkin karena kemasannya belum cukup "Instagramable". Atau mungkin karena kita sendiri belum cukup percaya dengan apa yang tumbuh di tanah sendiri. Pertemuan sore itu berakhir dengan secangkir Americano dan segunung tanya. Tapi juga sebuah tekad: Bahwa kopi Bali tak boleh hanya jadi kenangan. Bahwa petani lokal tak boleh jadi penonton. Bahwa anak-anak muda masih bisa mencintai kopi dari tanahnya sendiri—asal diberi ruang, diberi cerita, diberi tempat di cangkir hari-hari mereka. Karena mungkin, perubahan besar itu tak dimulai dari pabrik atau kampanye mentereng, tapi dari satu keputusan sederhana: memesan kopi Bali di coffee shop, di kota yang tanahnya masih subur oleh cita rasa sendiri. (*) (Menot Sukadana)
Baca juga :
• Tangan-Tangan yang Merangkai Warisan
• Jejak Piksel Para Penguasa
• Secangkir Optimisme di Tengah Kabar Buruk Pers











.png)

.jpeg)
.png)