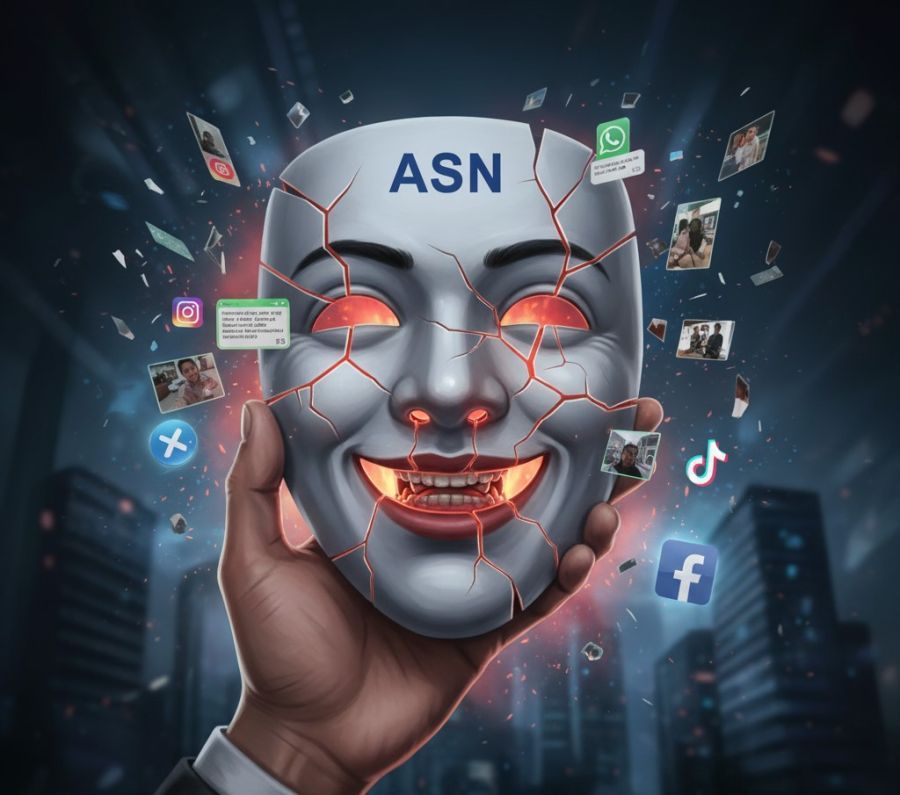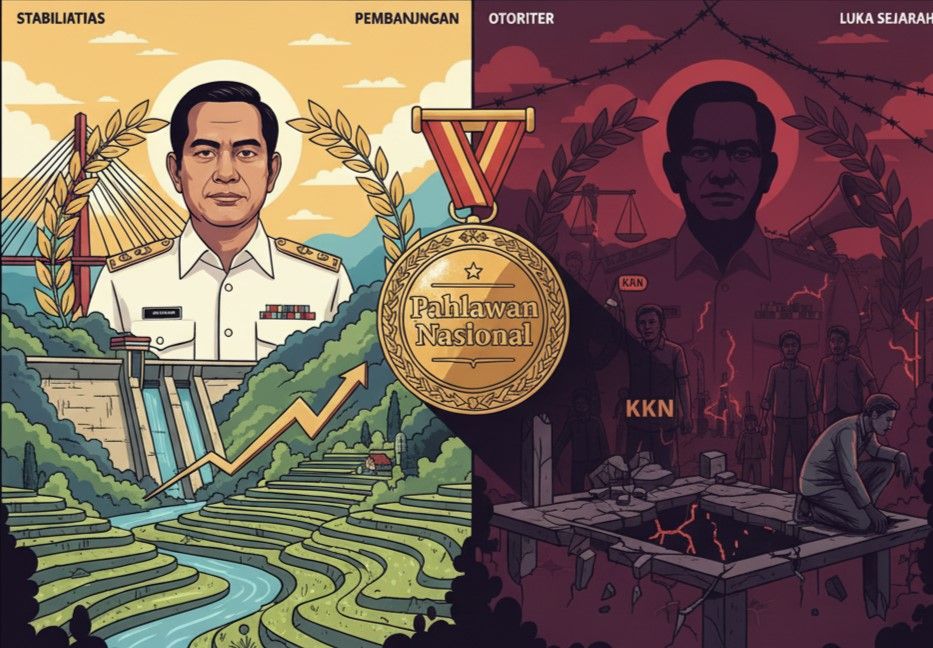Belajar Bahagia dari Indonesia

DI DUNIA yang semakin mengukur kesejahteraan dengan angka ekonomi dan kemajuan teknologi, Indonesia muncul sebagai anomali yang menarik.
Meski berada di jajaran negara berkembang dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang masih jauh tertinggal dari negara-negara maju, Indonesia secara konsisten menempati peringkat atas dalam survei kebahagiaan global.
Apa yang membuat orang Indonesia bahagia? Bagaimana mungkin masyarakat tetap tersenyum ketika pendapatan, pendidikan, dan layanan publik belum sebanding dengan negara-negara kaya?
Video dokumenter pendek dari channel YouTube Asianometry, “Why Are Indonesians Happy Despite Having Low Incomes?”, mengurai misteri ini dengan pendekatan yang tajam namun penuh empati.
Data, wawancara, dan analisis sosial dibungkus dalam narasi yang mudah dipahami, menyuguhkan gambaran tentang wajah masyarakat Indonesia yang bahagia bukan karena apa yang mereka punya, tapi karena bagaimana mereka hidup bersama.
Secara ekonomi, Indonesia memang belum berada di posisi yang membanggakan. PDB per kapita Indonesia berada di kisaran USD 4.700 (2023), tertinggal jauh dibanding negara-negara maju seperti Singapura atau Jepang.
Namun dalam laporan Gallup World Poll, sekitar 90% responden Indonesia mengaku mereka tersenyum atau tertawa pada hari sebelumnya. Indonesia bahkan secara konsisten berada di atas negara-negara kaya dalam indeks emosi positif.
Inilah yang disebut sebagai paradoks kebahagiaan Indonesia, yakni rendah secara evaluasi hidup jangka panjang, namun tinggi dalam kebahagiaan harian. Banyak orang Indonesia mungkin tidak merasa hidup mereka “ideal”, namun dalam keseharian, mereka merasa cukup—dan itu membuat mereka bahagia.
Kolektivisme
Salah satu jawaban utama atas paradoks ini adalah budaya kolektivisme yang begitu kuat mengakar di masyarakat Indonesia. Budaya ini menempatkan kepentingan kelompok, keluarga, dan komunitas di atas kepentingan pribadi.
Menurut Hofstede Cultural Dimensions, Indonesia memiliki skor individualisme yang sangat rendah, bahkan termasuk yang paling rendah di dunia.
Nilai-nilai seperti gotong royong, kerja bakti, membantu tetangga tanpa pamrih, hingga tradisi kenduri dan arisan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang mempererat ikatan sosial.
Dalam situasi sulit pun, masyarakat bisa saling menopang. Ketika satu orang sakit, tetangga datang membantu. Ketika ada acara pernikahan atau kematian, satu kampung ikut menyumbang tenaga dan makanan.
Video ini menyoroti beberapa contoh nyata, seperti kegiatan warga membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Tidak dibayar, tidak disuruh, tapi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Kebahagiaan di sini muncul dari rasa memiliki dan diterima, bukan dari apa yang dimiliki secara materi.
Agama dan Spiritualitas
Indonesia adalah negara dengan tingkat religiositas tinggi. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan populasi besar lainnya beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan lokal. Kegiatan keagamaan, baik yang bersifat spiritual maupun sosial, memberikan makna hidup sekaligus menjadi wadah untuk mempererat hubungan sosial.
Tradisi memberi seperti zakat, sedekah, dan gotong royong berbasis masjid menciptakan rasa solidaritas dan keadilan sosial.
Dalam video, disebutkan bahwa Indonesia memiliki salah satu skor tertinggi dalam “Indeks Kemurahan Hati” yang dibuat oleh World Giving Index. Memberi kepada orang lain, membantu yang kurang beruntung, dan berbagi rezeki adalah bagian dari identitas moral masyarakat.
Agama juga memberikan ketenangan batin. Dalam situasi ekonomi sulit, banyak orang Indonesia menyerahkan harapan pada Tuhan. “Rezeki sudah diatur,” kata mereka. Kepercayaan seperti ini, walau dianggap pasif oleh sebagian orang, justru bisa menjadi bantalan psikologis yang ampuh dalam menghadapi ketidakpastian.
Meskipun urbanisasi meningkat, sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan atau semi-perkotaan. Di tempat-tempat ini, waktu berjalan lebih lambat, biaya hidup lebih rendah, dan tekanan kompetitif tidak sekuat di kota besar.
Video ini menunjukkan bahwa meski fasilitas di desa terbatas, masyarakat justru lebih rileks. Mereka punya waktu untuk keluarga, ngobrol dengan tetangga, atau sekadar duduk di warung kopi.
Ini berbeda dengan kehidupan kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, di mana kemacetan, tuntutan kerja, dan tekanan sosial membuat banyak orang merasa kesepian dan stres.
Akankah Bertahan?
Meski budaya kolektivisme masih kuat, modernisasi membawa tantangan. Urbanisasi cepat, meningkatnya konsumsi media sosial, dan gaya hidup individual mulai merobek ikatan sosial. Video ini menyiratkan kekhawatiran yaitu apakah nilai-nilai luhur itu akan bertahan dalam arus zaman?
Generasi muda semakin terpapar budaya barat yang mengedepankan pencapaian individu. Kebahagiaan pun mulai diukur dari apa yang diposting di Instagram, bukan dari siapa yang hadir saat kita sakit.
Di sinilah pentingnya peran negara, institusi pendidikan, dan komunitas lokal. Pemerintah perlu mendukung kebijakan yang memperkuat ikatan sosial—misalnya ruang publik yang ramah interaksi, penguatan sistem gotong royong, dan penghargaan terhadap kearifan lokal.
Bisnis juga harus memahami bahwa produk atau jasa yang disesuaikan dengan semangat kebersamaan akan lebih diterima.
Esai ini bukan untuk memuliakan kemiskinan atau membenarkan ketimpangan ekonomi. Tetapi ada pelajaran besar dari masyarakat Indonesia, bahwa kebahagiaan tidak selalu mengikuti kurva ekonomi. Ada dimensi lain—rasa diterima, merasa cukup, dan hidup bersama—yang lebih menentukan dalam keseharian.
Di tengah dunia yang semakin individualistik dan kompetitif, Indonesia menjadi pengingat, bahwa mungkin, kita terlalu keras mengejar “hidup yang sempurna” dan lupa menjalani hari dengan rasa syukur. Kebahagiaan bisa sesederhana tertawa bersama tetangga atau berbagi nasi bungkus di ujung jalan. (*)
Angga Wijaya (Jurnalis tinggal di Denpasar, Bali)