Influencer Perlu Sertifikasi?
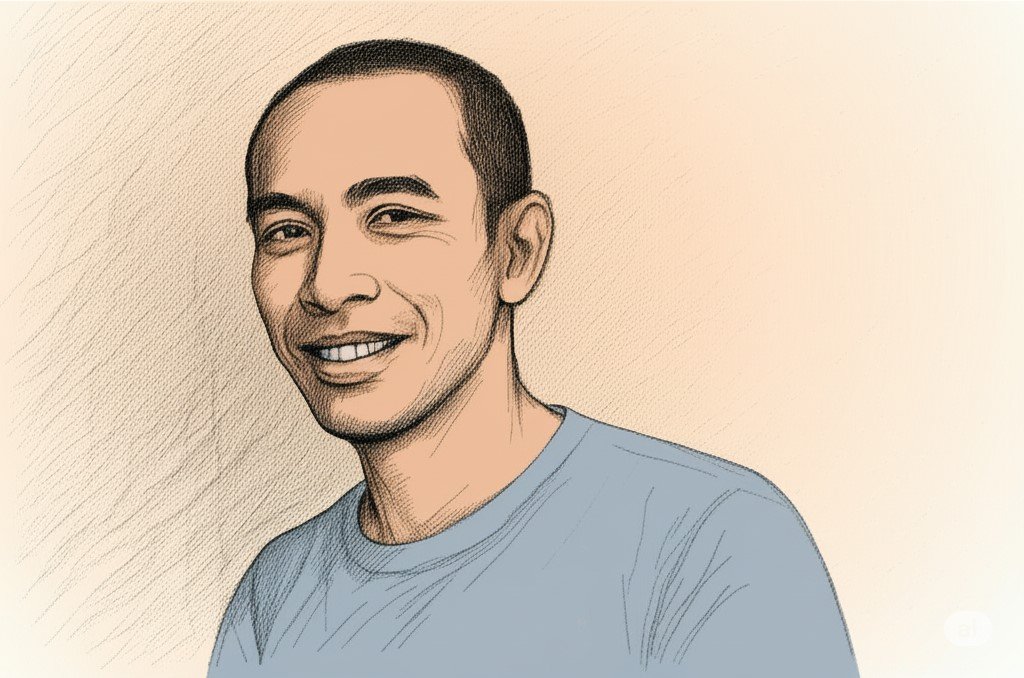
INFLUENCER kini bukan lagi sekadar pengisi ruang hiburan di media sosial. Mereka telah menjelma sebagai figur yang menentukan arus konsumsi, memengaruhi pilihan politik, hingga menggiring publik pada keputusan finansial. Tetapi di balik popularitas yang kerap berbuah pundi-pundi rupiah, muncul pertanyaan serius: apakah mereka cukup hanya bermodal jumlah pengikut, atau perlu sertifikasi agar bisa disebut kompeten?
Sejumlah negara telah memberi jawaban tegas. Uni Emirat Arab mewajibkan setiap influencer yang melakukan promosi berbayar memiliki lisensi resmi dari National Media Council. Biayanya tidak kecil, namun aturan ini menegaskan bahwa influencer diperlakukan setara dengan profesi formal yang tunduk pada regulasi. Tiongkok bahkan lebih jauh lagi: influencer yang berbicara soal kesehatan, keuangan, hukum, atau pendidikan wajib memiliki sertifikat keahlian profesional. Tanpa itu, akun mereka bisa diblokir. Prancis juga sudah mengikat influencer dengan undang undang yang melarang promosi produk berisiko tanpa izin serta mewajibkan transparansi iklan. Langkah langkah tersebut lahir dari kesadaran bahwa pengaruh influencer tidak bisa dibiarkan liar.
Indonesia tampaknya baru bersiap menapaki jalan itu. Otoritas Jasa Keuangan berencana mewajibkan sertifikasi bagi influencer yang terlibat dalam promosi produk pasar modal. Ini wajar, mengingat maraknya praktik manipulatif yang menjual mimpi cepat kaya melalui saham, kripto, atau investasi digital. Tetapi, apakah cukup hanya di bidang keuangan? Bukankah publik juga terpapar konten kesehatan yang menyesatkan, promosi gaya hidup instan yang menormalisasi utang konsumtif, atau endorsement politik yang memoles citra tanpa etika?
Pertanyaan lebih dalam: apa yang membuat seorang influencer layak dipercaya? Apakah sekadar popularitas, atau ada standar kompetensi yang mesti diakui secara formal? Jika wartawan memiliki Uji Kompetensi Wartawan untuk memastikan profesionalisme dan etika dalam menyampaikan informasi, mengapa influencer yang memengaruhi jutaan orang dibiarkan tanpa pagar serupa?
Uji Kompetensi Wartawan lahir dari kebutuhan untuk menjaga martabat profesi jurnalis. Di sana wartawan diuji tidak hanya pada keterampilan teknis menulis berita, tetapi juga pada pemahaman etika, kode perilaku, dan tanggung jawab sosial. Analogi ini tepat untuk menggambarkan kebutuhan terhadap semacam uji kompetensi influencer. Tanpa standar kompetensi, ruang digital hanya akan diisi oleh suara suara yang paling keras, bukan yang paling benar.
Masalahnya, sertifikasi selalu menimbulkan resistensi. Ada yang menilai hal ini bisa membatasi kreativitas, membebani profesi yang tumbuh organik dari spontanitas, bahkan dianggap sebagai bentuk sensor terselubung. Tetapi di sisi lain, kita tidak bisa menutup mata pada kerugian nyata yang muncul dari konten tanpa tanggung jawab. Banyak kasus kerugian finansial masyarakat kecil bermula dari ajakan influencer. Banyak juga persepsi publik soal kesehatan terbentuk dari klaim tanpa dasar ilmiah. Di titik ini, membiarkan influencer tanpa regulasi sama artinya menyerahkan ruang publik kepada logika kapital murni: siapa yang bayar lebih, dialah yang bersuara paling nyaring.
Sertifikasi bukan berarti membungkam. Ia justru bisa menjadi mekanisme untuk menegakkan tanggung jawab. Sertifikasi dapat disusun bertingkat: ada sertifikasi umum yang menekankan etika, ada pula sertifikasi khusus sesuai bidang. Seorang influencer yang bicara soal investasi harus memahami instrumen keuangan, sama seperti seorang dokter yang bicara kesehatan harus berlisensi. Prinsipnya sederhana: semakin besar pengaruh, semakin besar pula tanggung jawab.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah sertifikasi perlu, melainkan kapan dan bagaimana Indonesia berani mengambil langkah itu. Apakah kita akan menunggu lebih banyak korban dari promosi menyesatkan, atau mulai merancang standar sebelum terlambat?
Influencer lahir dari demokratisasi ruang digital, tetapi demokrasi tanpa standar hanya akan melahirkan kekacauan. Sertifikasi mungkin bukan solusi tunggal, tetapi ia adalah pintu masuk menuju ekosistem digital yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih bertanggung jawab. Pada akhirnya, publik berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan sekadar konten yang viral. Dan untuk itu, sertifikasi bagi influencer bukan lagi wacana pinggiran; ia sudah menjadi kebutuhan mendesak. (*)
Menot Sukadana (Jurnalis & Pegiat Media di Bali)










