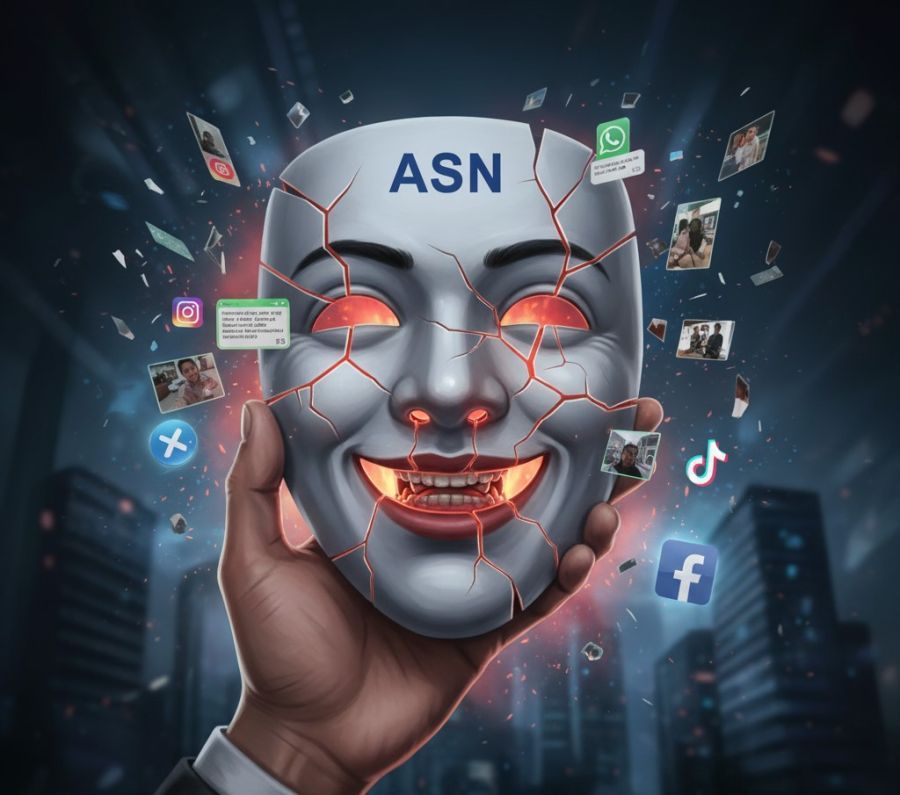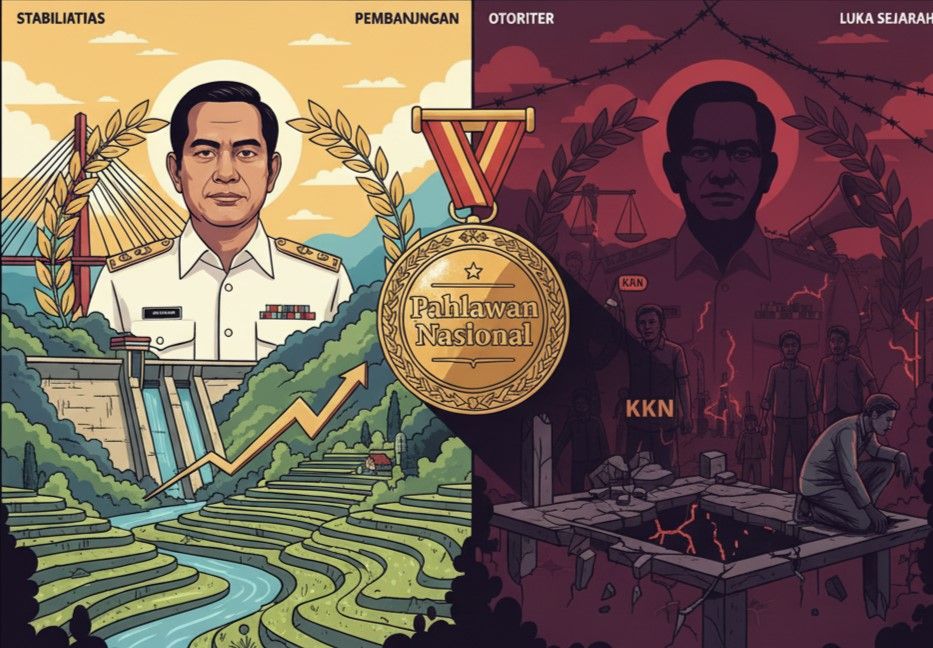Gas Oplosan dan Subsidi

KASUS penggerebekan praktik pengoplosan gas elpiji di Kuta Utara, Badung, kembali membuka mata tentang rapuhnya tata kelola energi bersubsidi di Indonesia. Tindakan seorang individu yang menyalahgunakan tabung gas 3 kilogram untuk dioplos menjadi ukuran lebih besar bukanlah sekadar tindak pidana ekonomi, melainkan juga cerminan dari kelemahan pengawasan negara atas distribusi subsidi yang seharusnya berpihak pada masyarakat kecil.
Gas elpiji 3 kilogram sejak awal memang dirancang sebagai jaring pengaman energi untuk kelompok miskin dan rentan. Namun, praktik yang terungkap di Bali menunjukkan bahwa instrumen kebijakan tersebut mudah diselewengkan untuk mencari keuntungan pribadi. Satu orang pelaku mampu mengubah puluhan tabung setiap hari, meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah per bulan, bahkan membeli kendaraan operasional dari hasil kejahatan itu. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: di mana posisi negara dalam memastikan subsidi benar-benar tepat sasaran?
Dari sisi penegakan hukum, kepolisian patut diapresiasi atas keberhasilan mengungkap dan menindak tegas kasus ini. Namun, sebagaimana telah berulang kali terjadi, pengungkapan pelaku tidak otomatis menyelesaikan akar masalah. Subsidi gas masih rentan bocor karena lemahnya rantai pengawasan, mulai dari agen, pengecer, hingga konsumen. Ketiadaan sistem distribusi berbasis data dan teknologi membuat tabung bersubsidi sering kali tidak sampai ke rumah tangga miskin yang seharusnya menjadi prioritas.
Lebih jauh, kasus ini menyingkap dilema klasik kebijakan subsidi di Indonesia. Di satu sisi, subsidi energi menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Di sisi lain, subsidi yang dibiarkan tanpa pengawasan ketat justru melahirkan ruang gelap bagi praktik manipulasi. Ketika gas 3 kilogram yang mestinya menyokong dapur rakyat miskin beralih menjadi barang dagangan ilegal, maka negara sejatinya telah gagal dalam menjalankan amanah keadilan sosial.
Editorial ini menekankan bahwa pemerintah tidak boleh lagi bersikap reaktif. Penindakan hukum penting, tetapi jauh lebih mendesak adalah pembenahan sistem distribusi. Digitalisasi penyaluran, pencatatan berbasis Nomor Induk Kependudukan, hingga pembatasan distribusi di titik akhir adalah langkah yang harus segera dipercepat. Tanpa itu semua, pengoplosan akan terus berulang, berganti wajah, dan merugikan masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi.
Ada pula dimensi moral yang tidak boleh diabaikan. Ketika keuntungan pribadi ditempatkan di atas kepentingan publik, maka nilai gotong royong dan rasa keadilan ikut terkikis. Negara hadir bukan sekadar untuk memburu pelaku setelah kejahatan terjadi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap tetes subsidi benar-benar sampai pada mereka yang membutuhkan. Hanya dengan demikian kepercayaan publik dapat dipulihkan dan subsidi kembali berfungsi sebagai penopang kesejahteraan rakyat kecil.
Kasus di Bali menjadi peringatan bahwa tata kelola energi bersubsidi masih jauh dari ideal. Pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawasan harus bergerak bersama membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Jika tidak, pengoplosan gas akan terus menjadi bisnis gelap yang merugikan negara sekaligus menjerat rakyat miskin pada lingkaran ketidakadilan.
Subsidi adalah janji negara untuk melindungi yang lemah. Sudah semestinya janji itu dijaga dengan penuh keseriusan. (*)