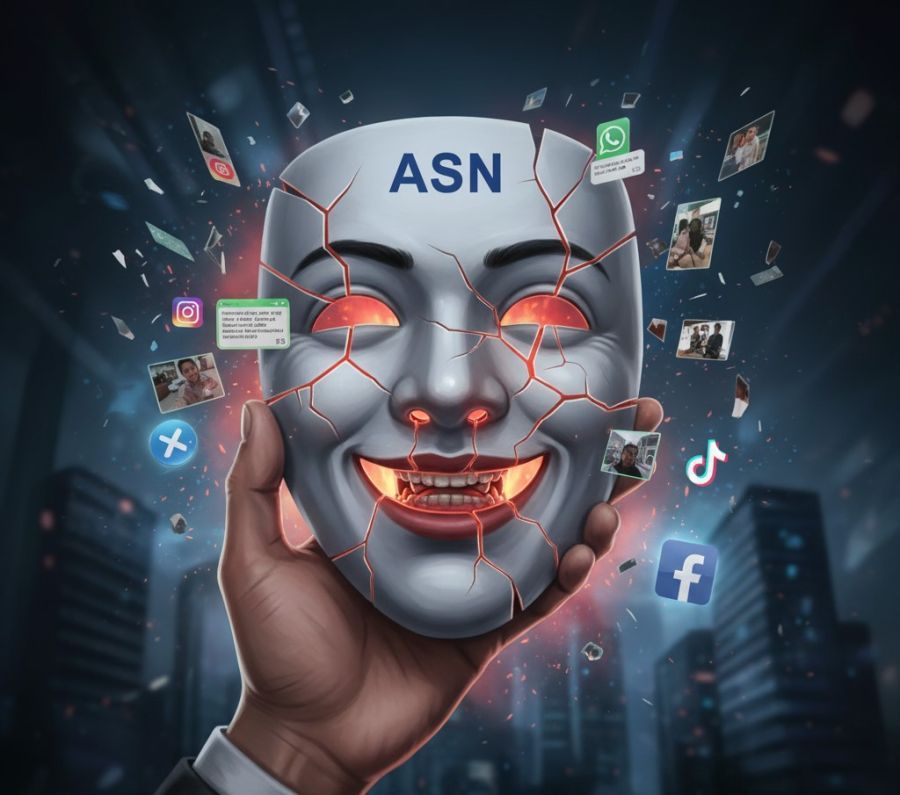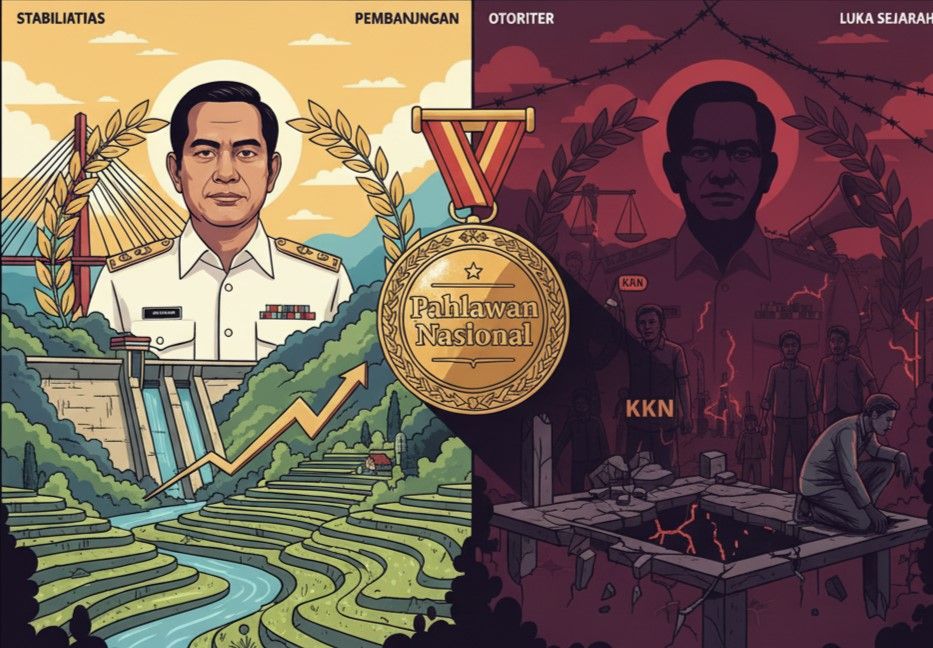Belajar dari Krisis

SITUASI politik dan ekonomi yang tidak stabil selalu menghadirkan kecemasan baru dalam kehidupan masyarakat. Gejolak pasar, demonstrasi besar, hingga kebijakan pemerintah yang kerap berubah menimbulkan efek berantai. Kepercayaan investor terguncang, kurs rupiah melemah, dan harga kebutuhan pokok merangkak naik. Namun di balik turbulensi makro itu, yang paling rentan sesungguhnya adalah rumah tangga biasa. Pada akhirnya, badai ekonomi akan bermuara di meja makan, menentukan apakah nasi tetap tersaji dengan layak atau justru harus dikurangi porsinya.
Sejarah memberi kita banyak pelajaran. Krisis moneter 1998 adalah contoh nyata bagaimana politik dan ekonomi saling terkait. Inflasi melambung, rupiah terperosok hingga ribuan persen, harga sembako tak terkendali. Bagi keluarga sederhana, krisis itu berarti menukar lauk dengan garam atau mengurangi porsi makan dari tiga kali menjadi dua kali sehari. Bagi mereka yang tidak memiliki tabungan, krisis menjadi jurang yang menelan daya tahan, menjatuhkan jutaan orang ke dalam kemiskinan baru.
Krisis serupa tidak hanya terjadi di Indonesia. Yunani pada 2008 hingga 2010 terhimpit krisis utang yang memaksa pemerintah memangkas anggaran besar-besaran. Rakyat harus hidup dalam kebijakan pengetatan yang menyakitkan. Subsidi dipangkas, pajak dinaikkan, kesempatan kerja menyempit. Sementara di Argentina, krisis keuangan berulang kali membuat masyarakat terbiasa menyimpan tabungan dalam bentuk dolar atau emas agar tidak tergerus depresiasi peso. Dari berbagai pengalaman itu, kita belajar bahwa rumah tangga adalah benteng terakhir yang harus disiapkan untuk bertahan bahkan ketika negara limbung.
Dalam konteks ini, ada dua strategi dasar yang patut dipertimbangkan oleh masyarakat di tengah ketidakpastian: selektivitas dalam pengeluaran dan penyediaan dana darurat.
Pertama, selektivitas dalam pengeluaran. Masyarakat perlu membedakan dengan tegas antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan primer seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal harus menjadi prioritas. Sementara kebutuhan sekunder dan tersier, seperti gawai terbaru, liburan mewah, atau konsumsi yang bersifat gaya hidup, sebaiknya ditahan terlebih dahulu. Prinsip ini terdengar sederhana, tetapi penerapannya kerap sulit. Tekanan sosial dan arus konsumsi membuat banyak orang tergoda untuk membelanjakan lebih dari kemampuannya.
Krisis adalah momentum untuk kembali pada kesadaran mendasar. Hidup sederhana bukanlah kekurangan, melainkan strategi bertahan. Pada tahun 1998, banyak keluarga melewati badai karena berani menurunkan standar konsumsi. Daging diganti dengan tempe, kendaraan pribadi diganti dengan transportasi umum, pakaian lama dijahit ulang alih-alih membeli baru. Kesadaran inilah yang kini perlu dibangkitkan kembali.
Kedua, penyediaan dana darurat. Idealnya, setiap rumah tangga memiliki cadangan setara tiga hingga enam bulan pengeluaran bulanan. Dana ini tidak boleh dipakai untuk kebutuhan rutin, melainkan hanya digunakan ketika kondisi benar-benar genting. Kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau inflasi yang melonjak adalah contoh situasi yang membutuhkan dana darurat. Simpanan bisa berbentuk rekening terpisah, emas, atau instrumen likuid lain yang mudah dicairkan.
Pelajaran dari Argentina menunjukkan bahwa mereka yang mampu bertahan adalah yang memiliki simpanan dalam bentuk yang tidak mudah tergerus inflasi. Di Indonesia, sebagian masyarakat juga mulai terbiasa menabung dalam bentuk emas atau dolar untuk mengamankan nilai kekayaan. Diversifikasi aset adalah langkah bijak. Bukan hanya menjaga nilai tabungan, tetapi juga memberi rasa aman psikologis bahwa keluarga masih memiliki pegangan di tengah badai.
Kesadaran ini tidak boleh berhenti pada situasi krisis. Ia perlu menjadi pola hidup yang konsisten. Bedanya, dalam masa ekonomi normal, orang cenderung lengah dan merasa stabilitas akan berlangsung selamanya. Padahal sejarah membuktikan tidak ada stabilitas yang kekal. Politik bisa bergejolak, ekonomi bisa merosot, dan bencana alam atau pandemi bisa datang sewaktu-waktu.
Krisis 1998 menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki tabungan lebih mampu melewati badai. Krisis Yunani menegaskan pentingnya solidaritas komunitas, saling berbagi bahan pangan, membuka dapur umum, hingga gotong royong membayar listrik. Sementara pengalaman Argentina memberi pelajaran bahwa diversifikasi aset adalah jalan keluar dari inflasi berkepanjangan.
Ini bukan hanya bicara soal menekan pengeluaran, melainkan tentang kesadaran menjaga fondasi rumah tangga. Sebab janji stabilitas dari elite politik bisa goyah, kebijakan ekonomi bisa berubah, dan bencana bisa datang kapan saja. Yang paling nyata dan bisa diandalkan adalah daya tahan keluarga itu sendiri.
Ekonom John Maynard Keynes pernah menekankan bahwa kestabilan ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada kemampuan masyarakat menyesuaikan diri dengan guncangan. Sementara filsuf Yunani, Epictetus, mengingatkan bahwa bukan peristiwa yang menghancurkan kita, melainkan cara kita merespons peristiwa itu. Dua pandangan ini bertemu dalam satu pesan: ketangguhan lahir dari kesadaran, bukan dari ilusi stabilitas.
Hari ini, kondisi Indonesia memang belum sampai pada krisis selevel 1998. Namun tanda-tanda ketidakpastian sudah terasa. Karena itu, langkah paling bijak adalah menyiapkan diri sejak dini. Seperti pepatah lama yang selalu relevan, sedia payung sebelum hujan. Dan dalam badai ekonomi, payung itu tidak lain adalah tabungan, kesederhanaan, serta kebijaksanaan rumah tangga dalam mengelola hidup. (*)
Menot Sukadana (Jurnalis & Pegiat Media di Bali)