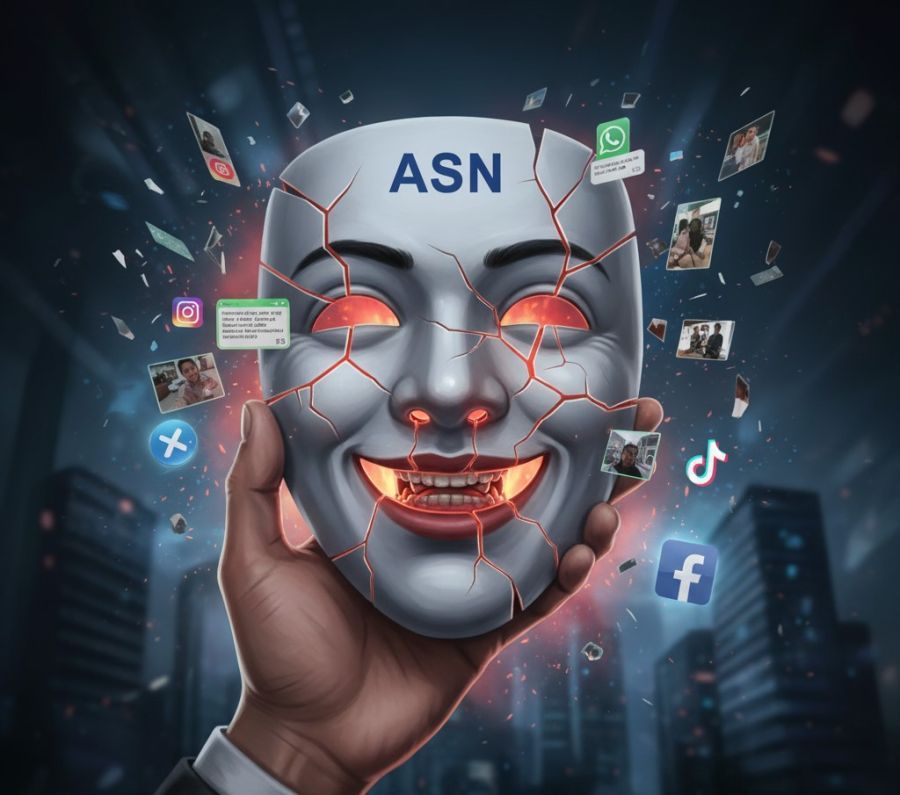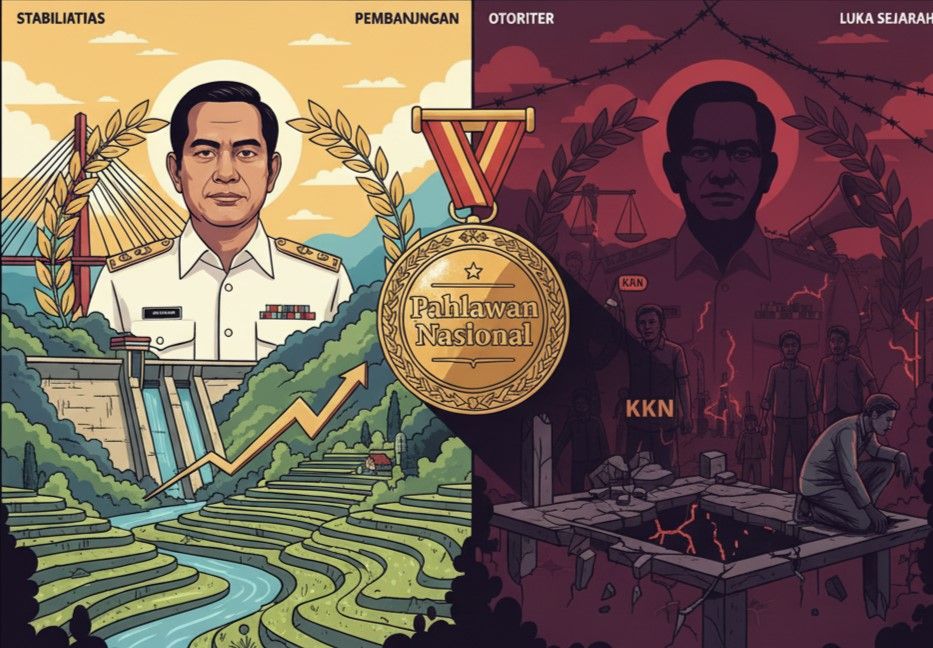Ketika Diam Lebih Bernilai dari Kata

MANUSIA modern hidup di zaman yang menuntut setiap hal untuk dijelaskan. Setiap ucapan harus diberi konteks, setiap keputusan mesti disertai alasan, dan setiap kesalahpahaman dianggap wajib diluruskan seketika. Media sosial, dengan logika instannya, melipat seluruh proses berpikir menjadi serangkaian reaksi spontan yang seolah menjadi ukuran kebenaran. Di dunia yang serba cepat dan terbuka ini, keheningan kehilangan tempatnya. Padahal dalam sejarah panjang peradaban, diam selalu menjadi bagian dari kebijaksanaan: ruang di mana manusia menimbang, mendengar, dan memahami sebelum berbicara.
Kita sering lupa bahwa komunikasi tidak selalu membutuhkan kata. Ia adalah seni memahami, bukan sekadar menyampaikan. Dalam tradisi Timur, manusia diajarkan untuk berbicara seperlunya dan mendengar selengkapnya. Dalam diam, seseorang bisa mengamati lebih dalam; dalam kesunyian, ia belajar memilah mana yang penting untuk diucapkan dan mana yang lebih baik disimpan. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara kebijaksanaan dan sekadar kepandaian berkata-kata. Manusia yang bijak tidak segera menanggapi setiap hal, karena ia tahu tidak semua hal pantas untuk ditanggapi.
Sosiolog komunikasi Edward T. Hall menyebut budaya seperti ini sebagai high-context communication, yaitu gaya berkomunikasi yang menempatkan makna di balik isyarat, bukan semata pada kata (Beyond Culture, 1976). Dalam masyarakat Timur, komunikasi dibangun bukan melalui kelantangan, tetapi melalui pemahaman halus atas situasi, ekspresi, dan diam itu sendiri. Adam Jaworski, dalam Silence: Interdisciplinary Perspectives (1997), bahkan menegaskan bahwa diam bukanlah ketiadaan pesan, melainkan bentuk komunikasi yang memiliki makna sosial, psikologis, dan spiritual. Dengan kata lain, ketika seseorang memilih untuk tidak berbicara, ia sebenarnya sedang menyampaikan sesuatu yang lebih dalam daripada kata-kata.
Namun zaman kita kini hidup dalam budaya keterbukaan yang sering kali salah arah. Keterbukaan dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu menjelaskan diri, bahkan untuk hal-hal yang sebetulnya tidak memerlukan penjelasan apa pun. Masyarakat modern menjadi terobsesi pada transparansi, tetapi kehilangan kedalaman. Di dunia digital, orang menuntut kejelasan di setiap situasi, bahkan terhadap hal-hal yang seharusnya dibiarkan menjadi misteri.
Psikolog Sherry Turkle dalam bukunya Reclaiming Conversation (2015) menulis bahwa masyarakat modern kehilangan kemampuan untuk berdiam dan merenung karena terbiasa bereaksi cepat terhadap segala sesuatu. Setiap notifikasi dianggap panggilan moral untuk merespons. Akibatnya, percakapan kehilangan kedalaman dan relasi kehilangan makna. Di balik dorongan untuk menjelaskan itu, sesungguhnya tersembunyi ketakutan: ketakutan untuk disalahpahami, untuk tidak dipercaya, atau untuk kehilangan simpati publik. Maka manusia berlomba-lomba menjelaskan dirinya tanpa henti, seolah hidupnya akan kehilangan makna bila diam terlalu lama.
Padahal, banyak persoalan tidak selesai dengan penjelasan, sebagaimana banyak luka tidak sembuh oleh kata-kata. Thomas J. Bruneau dalam studinya Communicative Silences (1973) menjelaskan bahwa diam bisa berfungsi sebagai bentuk kontrol diri, refleksi, bahkan perlawanan halus terhadap situasi sosial yang tidak produktif. Upaya untuk terus-menerus menjelaskan diri sering kali justru memperlebar jurang salah paham. Dalam komunikasi interpersonal, dalam politik, bahkan dalam kehidupan spiritual, penjelasan yang berlebihan bisa membuat pesan kehilangan makna. Kata yang diucapkan tanpa kesadaran hanya menjadi gema kosong. Di sisi lain, diam memberi ruang bagi makna tumbuh sendiri. Diam bukan sekadar ketiadaan suara; ia adalah bentuk komunikasi tingkat tinggi, yang menuntut kendali diri, empati, dan kebijaksanaan.
Budaya Timur sudah lama memahami ini. Dalam falsafah Jawa, seperti dijelaskan Franz Magnis-Suseno dalam Etika Jawa (1997), berbicara dengan halus dan secukupnya adalah bentuk kesadaran moral, karena kata yang berlebihan dianggap bisa merusak harmoni sosial. Sementara Niels Mulder dalam Inside Indonesian Society (1996) mencatat bahwa masyarakat Indonesia cenderung menghindari konfrontasi langsung dan menilai diam sebagai bentuk penghormatan serta kedewasaan sosial.
Padahal diam tidak identik dengan kekosongan. Ia bisa berarti kesabaran, bisa pula ketegasan. Dalam banyak situasi, justru orang yang mampu menahan diri untuk tidak segera menjawab menunjukkan tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dibanding mereka yang bereaksi spontan. Orang yang memilih diam bukan karena tak mampu berbicara, melainkan karena tahu kata yang diucapkan pada waktu yang salah bisa lebih melukai daripada menenangkan.
Dalam konteks kepemimpinan, diam adalah bagian dari kebijaksanaan spiritual. Filsuf Timur seperti Lao Tzu dalam Tao Te Ching mengajarkan bahwa “diam adalah sumber kekuatan besar”, sementara Daisetz T. Suzuki melalui Zen Buddhism: Selected Writings (1956) menekankan bahwa keheningan adalah jalan menuju pencerahan. Pemimpin yang mampu menahan diri untuk tidak segera bereaksi sesungguhnya sedang mengelola energinya, bukan sekadar menunda jawaban, melainkan menata batin.
Kita mengenal beberapa tokoh bangsa yang diamnya berbicara lebih keras daripada pidatonya. Megawati Soekarnoputri adalah salah satu contoh. Dalam dinamika politik yang panas dan penuh tekanan, ia sering kali memilih tidak berkomentar. Dalam dunia politik yang begitu bergantung pada pernyataan, sikap itu dianggap lamban. Namun sejarah memperlihatkan bahwa diamnya Megawati justru menjadi bentuk komunikasi paling efektif: diam yang penuh perhitungan, diam yang menyimpan daya. Ia tidak berbicara untuk menjelaskan dirinya, melainkan untuk membiarkan waktu bekerja.
BJ Habibie memberi contoh lain. Setelah keputusannya melepas Timor Timur pada 1999, ia menjadi sasaran kritik dan hujatan. Banyak yang mendesak agar ia menjelaskan alasan di balik kebijakan itu secara panjang lebar. Namun Habibie memilih tidak banyak bicara. Ia hanya berkata pendek, “Saya melakukan apa yang saya yakini benar.” Kalimat itu sederhana, tapi menyimpan kedalaman keyakinan seorang negarawan. Dua puluh lima tahun kemudian, bangsa ini menilai keputusannya dengan kacamata berbeda. Waktu membuktikan bahwa diam Habibie bukan tanda kelemahan, melainkan keteguhan.
Lalu ada KH Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang menghadapi badai politik dengan senyum. Ia bisa saja membalas semua serangan dengan pidato keras, tapi ia memilih diam, atau tertawa. Tawa itu bukan bentuk pengabaian, melainkan cermin dari kematangan spiritual. Dalam senyum itu, Gus Dur menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak perlu menjelaskan segala sesuatu kepada mereka yang tidak mau mendengar.
Dalam literatur kepemimpinan modern, Robert K. Greenleaf dalam Servant Leadership (1977) menulis bahwa pemimpin sejati bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling dalam mendengar. Dan Daniel Goleman, dalam Emotional Intelligence (1995), menegaskan bahwa kecerdasan emosional sering kali justru tampak dari kemampuan seseorang menunda reaksi, bukan dari kemampuan membalas dengan cepat.
Ketiga tokoh itu menunjukkan sisi lain dari kepemimpinan: bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari kelantangan suara, tetapi dari kemampuan mengatur waktu untuk bicara dan waktu untuk diam. Mereka mengingatkan bahwa penjelasan bukan selalu tanda keterbukaan, sebagaimana diam bukan selalu tanda kelemahan. Dalam dunia yang serba gaduh, pemimpin yang berani memilih diam menunjukkan kekuatan moral yang berbeda.
Namun bukan hanya pemimpin yang perlu belajar seni diam. Kita semua, sebagai manusia sosial yang hidup di tengah kebisingan informasi, perlu memahami nilai keheningan. Dunia digital telah mengaburkan batas antara reaksi dan refleksi.
Edgar H. Schein dalam Humble Inquiry (2013) menulis bahwa dalam dunia modern yang serba cepat, kemampuan untuk bertanya dengan rendah hati dan mendengarkan dengan empati menjadi inti dari komunikasi yang bermakna. Diam adalah bagian penting dari proses itu, bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap makna dan keberadaan orang lain.
Diam memberi waktu bagi pikiran untuk menyaring emosi, bagi hati untuk menemukan keseimbangan. Ia bukan sikap pasif, melainkan ruang aktif untuk berpikir jernih. Dalam keheningan, manusia bisa mendengar lebih banyak, tentang orang lain, tentang keadaan, dan tentang dirinya sendiri. Dengan diam, seseorang tidak kehilangan suara; ia justru menemukan bentuk komunikasi yang lebih dalam.
Mungkin sudah saatnya kita meninjau kembali cara kita berkomunikasi di dunia modern. Tidak semua serangan layak ditanggapi, tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan, dan tidak semua tudingan harus dibantah. Terkadang, membiarkan waktu berbicara adalah pilihan yang paling arif. Karena pada akhirnya, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia menjelaskan dirinya, tetapi dari seberapa dalam ia memahami dirinya sendiri.
Diam adalah hakikat dari kematangan batin. Ia adalah ruang di mana manusia belajar untuk berdamai, dengan dirinya, dengan orang lain, dengan kehidupan. Dalam dunia yang semakin gaduh, barangkali diam adalah bentuk perlawanan yang paling lembut, tapi paling kuat. Karena seperti air yang mengalir di dasar sungai, ia tenang, tapi membawa kehidupan.
Pada akhirnya, hidup tidak menuntut kita untuk menjelaskan segalanya. Ia hanya menuntut kita untuk hidup dengan kesadaran dan kejujuran. Dan bagi mereka yang sudah berdamai dengan diri sendiri, penjelasan bukan lagi kebutuhan. Diam menjadi cukup. (*)
Menot Sukadana (Jurnalis, penggagas Podium Ecosystem: media, konsultan, gaya hidup & ruang publik)