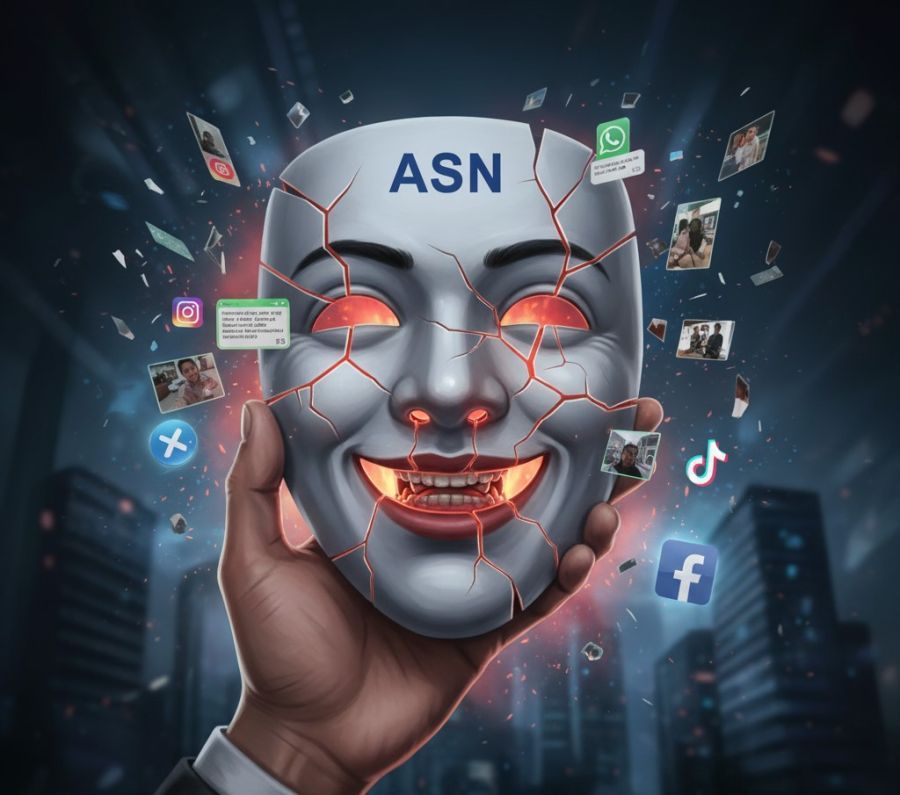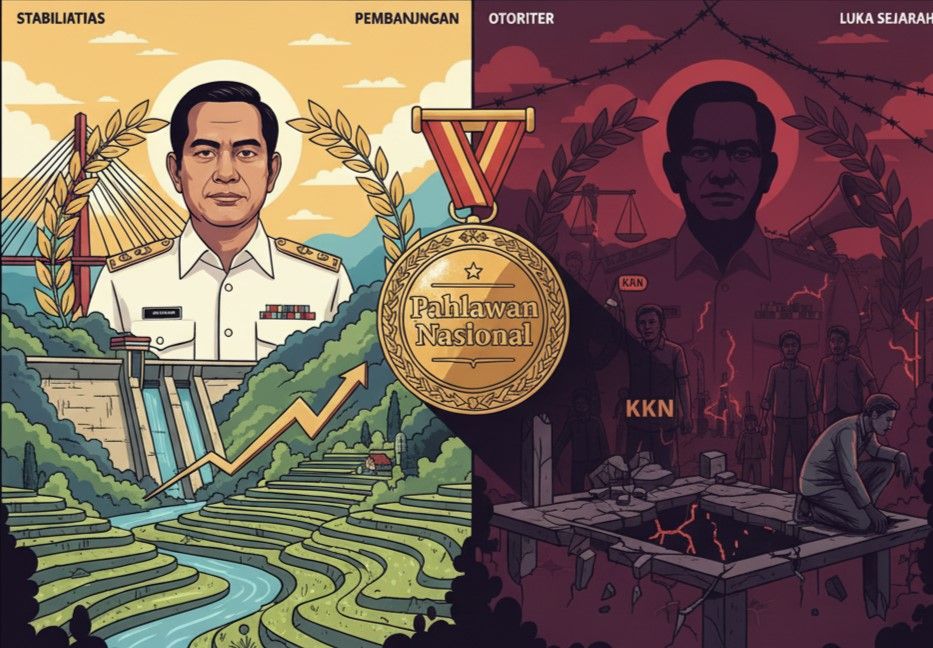Habibie, Ketika Kekuasaan Bukan Segalanya

PADA pagi 14 Oktober 1999, ruang sidang utama Gedung MPR/DPR di Senayan penuh sesak. Di tengah suhu politik yang panas pasca-Reformasi, Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie berdiri di podium, mengenakan jas hitam, dasi merah, dan kopiah khasnya. Suaranya tenang ketika membuka pidato pertanggungjawaban di hadapan para wakil rakyat. Ia tahu, pidato itu akan menentukan apakah ia masih layak memimpin republik yang sedang belajar berdiri kembali setelah tiga dekade dikuasai satu rezim.
Habibie tidak datang dari dunia politik. Ia adalah seorang insinyur, seorang teknokrat, yang tiba-tiba didorong masuk ke pusaran kekuasaan setelah Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Sebelumnya, ia adalah Wakil Presiden yang setia pada Soeharto, sekaligus arsitek utama industri strategis Indonesia, termasuk lahirnya pesawat N250 Gatotkaca yang terbang perdana pada 10 Agustus 1995. Namun sejarah bergerak cepat. Dalam waktu singkat, krisis ekonomi 1998 memporakporandakan negeri. Rupiah jatuh hingga Rp15.000 per dolar AS, inflasi menembus 80 persen, kerusuhan meledak di Jakarta dan kota-kota besar lain. Lalu, di tengah kekacauan itu, Habibie menerima tongkat estafet kepemimpinan.
Sebagai presiden selama 1 tahun 5 bulan, Habibie membawa perubahan besar. Ia menata ekonomi hingga nilai tukar rupiah perlahan pulih di kisaran Rp6.500 per dolar pada pertengahan 1999. Ia juga membuka pintu demokrasi selebar-lebarnya. Dalam masa pemerintahannya, lahir Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menghapus sistem izin dan sensor. Ia juga menggelar Pemilu demokratis pertama pasca-Orde Baru pada 7 Juni 1999, yang diikuti 48 partai politik. Pemilu itu menjadi tonggak kebangkitan demokrasi Indonesia.
Namun keberhasilannya di bidang demokrasi tidak serta-merta membuatnya populer. Banyak pihak masih memandangnya sebagai “orang Soeharto” dan simbol masa lalu yang hendak ditinggalkan. Sidang Umum MPR 1999 menjadi ujian moral terbesar bagi Habibie. Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban, sidang memutuskan untuk menolak laporan tersebut. Dari 678 anggota MPR yang hadir, 355 menolak dan 322 menerima, dengan satu suara abstain. Keputusan itu diumumkan secara terbuka pada malam 19 Oktober 1999.
Ketika Ketua MPR Amien Rais membacakan hasil pemungutan suara, banyak orang memperhatikan wajah Habibie. Ia tidak menunduk, tidak marah, tidak juga meneteskan air mata. Ia hanya tersenyum kecil, mengangguk pelan, lalu menyalami Amien Rais dan sejumlah tokoh politik satu per satu. Di ruang yang penuh intrik dan ambisi itu, ia memilih tenang.
Keesokan harinya, pada 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan tidak bersedia mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Dalam naskah memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006), ia menulis dengan bahasa yang jernih: “Saya tidak available untuk dicalonkan sebagai Presiden pada SU MPR Oktober 1999.”
Kalimat itu sederhana, tetapi menggetarkan. Ia bisa saja maju. Banyak tokoh, termasuk Amien Rais, saat itu menyarankan Habibie tetap ikut mencalonkan diri karena memiliki dukungan Golkar dan sebagian Fraksi ABRI. Namun Habibie memilih mundur. Ia menulis bahwa keputusan itu diambil karena merasa tidak memiliki legitimasi moral setelah pertanggungjawabannya ditolak. Bagi Habibie, kekuasaan tanpa legitimasi adalah bentuk penghianatan terhadap nurani.
Habibie memahami bahwa legitimasi tidak hanya datang dari angka dukungan, tapi dari kepercayaan publik. Ia memilih menolak jabatan yang masih bisa diraihnya. Dalam salah satu wawancara tahun 2006, Habibie berkata, “Kalau rakyat tidak percaya, bagaimana saya bisa memimpin? Saya tidak mau mempertahankan kekuasaan yang tidak lagi diberi kepercayaan.”
Pilihan itu mengejutkan banyak pihak. Indonesia sedang dalam masa transisi, dan kekuasaan sangat menggoda bagi siapa pun. Tapi Habibie menunjukkan bahwa dalam politik, ada yang lebih tinggi dari kekuasaan: kehormatan.
Sikap itu sejalan dengan keputusan penting lain yang ia ambil semasa berkuasa. Setelah menjadi presiden, ia tidak melanjutkan proyek ambisius yang ia bangun sendiri selama puluhan tahun: industri pesawat terbang nasional. Proyek N250 yang dilahirkan lewat IPTN di Bandung sempat dibekukan oleh IMF dalam paket kebijakan yang diteken Soeharto pada awal 1998. Setelah menjadi presiden, Habibie tidak mencabut pembekuan itu. Ia lebih memilih memulihkan ekonomi nasional dan mengembalikan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Padahal, dalam dirinya, pesawat itu bukan sekadar proyek. Dalam berbagai kesempatan, ia menyebut N250 sebagai “anak rohani” yang lahir dari keringat dan cinta bangsa.
Dalam wawancara tahun 2012 dengan Tempo, Habibie mengatakan, “Saya tahu, itu anak saya. Tapi anak itu harus menunggu waktu. Negara ini harus pulih dulu.” Kalimat itu menggambarkan betapa dalamnya rasa tanggung jawabnya terhadap bangsa, melebihi ambisi pribadinya sebagai ilmuwan dan teknokrat.
Banyak tokoh politik mungkin akan memilih sebaliknya. Mereka akan bertahan di kekuasaan dengan alasan stabilitas atau dukungan partai. Tapi Habibie memilih menjadi presiden yang tidak diperpanjang mandatnya, meski punya peluang untuk kembali. Ia tahu kapan harus datang dan kapan harus pergi.
Keputusan itu menjadikan Habibie sosok yang unik dalam sejarah republik ini. Ia adalah satu dari sedikit pemimpin yang meninggalkan jabatan bukan karena kalah, tapi karena sadar diri. Ia tidak tumbang oleh lawan, melainkan menang atas egonya sendiri. Ia kalah dalam voting, tapi menang dalam sejarah.
Sejarawan Anhar Gonggong pernah mengatakan dalam wawancara dengan Kompas (2019), “Habibie menunjukkan bahwa demokrasi memerlukan keteladanan moral. Ia meninggalkan kekuasaan bukan karena tidak mampu, tapi karena memilih menjaga martabatnya.” Kalimat itu seolah menjadi ringkasan perjalanan politik Habibie: pemimpin yang datang dari ruang mesin, bukan ruang kampanye; yang lebih percaya pada integritas daripada intrik.
Dua puluh lima tahun setelah peristiwa itu, pelajaran Habibie terasa semakin berharga. Di tengah dunia politik Indonesia yang kini sarat ambisi dan saling sandera kekuasaan, kisah Habibie mengingatkan bahwa politik sejati adalah ruang pengabdian, bukan perlombaan untuk bertahan. Ia tidak punya pasukan, tidak punya dinasti, tidak punya jaringan modal raksasa. Tapi ia punya sesuatu yang lebih berharga dari semua itu: kebesaran jiwa.
Habibie wafat pada 11 September 2019 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, dalam usia 83 tahun. Saat jenazahnya disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, ribuan orang berbaris di tepi jalan, menundukkan kepala, memberi penghormatan terakhir. Mereka mungkin tidak semua tahu sejarah sidang MPR 1999, tapi mereka tahu satu hal: Habibie adalah pemimpin yang jujur.
Ia datang tanpa ambisi, bekerja tanpa pamrih, dan pergi tanpa dendam. Ia meninggalkan pesan yang sederhana tapi abadi: “Jadilah mata air, bukan genangan. Air yang memberi kehidupan, bukan yang menunggu disembah.”
Dan dalam sejarah bangsa yang penuh perebutan tahta, Habibie membuktikan bahwa kadang pemimpin terbesar adalah yang tahu kapan harus berhenti. (*)
(riki/sukadana)