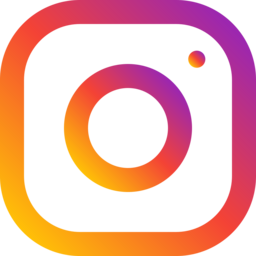Selembar Kain yang Terkoyak Makna
 Editor |
30 April 2025 | 19:10:00 WITA
Editor |
30 April 2025 | 19:10:00 WITA

SEHELAI kain. Begitu ringkasnya kita menyebutnya. Namun, di balik anyaman benang dan lilitan warna, tersembunyi kisah panjang sebuah peradaban. Di Bali, endek bukan sekadar penutup tubuh, melainkan jejak ingatan kolektif, bisikan leluhur yang terjalin dalam motif-motif yang tak lekang oleh waktu. Ia adalah identitas yang dikenakan, kebanggaan yang diwariskan. Namun, zaman memang tak pernah berhenti beringsut. Kabar yang dibawa Putri Koster bagai angin kelabu yang menerpa pagi Pulau Dewata. Delapan puluh tiga persen endek yang kini membanjiri pasar Bali ternyata bukan lagi sentuhan kasih pengrajin lokal, bukan lagi degup jantung tradisi yang ditenun dengan sabar. Ia lahir dari deru mesin-mesin pabrik di seberang sana, di Troso yang jauh. Sebuah paradoks yang menyesakkan: di lumbungnya sendiri, padi justru digantikan bulir-bulir imitasi. Kita tahu, modernitas sering kali hadir dengan janji efisiensi dan harga yang lebih murah. Namun, ada harga yang tak ternilai yang ikut tergerus dalam arus industrialisasi ini. Kehilangan keunikan, hilangnya cerita di setiap helai benang yang ditenun dengan tangan. Endek yang diproduksi massal adalah komoditas tanpa jiwa, selembar kain tanpa narasi. Ia hadir tanpa jejak keringat perajin, tanpa doa yang terbisikkan saat motif demi motif dirangkai. Lebih jauh lagi, kabar tentang motif songket yang dibajak oleh industri bordir menambah pilu. Hak kekayaan intelektual komunal, yang seharusnya menjadi payung pelindung bagi kearifan lokal, ternyata tak mampu membendung gelombang peniruan yang vulgar. Ini bukan lagi soal persaingan dagang yang sehat, melainkan sebuah perampasan identitas yang dilakukan secara terang-terangan. Sastrawan besar pernah menulis tentang "kata yang hilang di tengah riuh." Dalam konteks ini, mungkin yang hilang adalah makna dari selembar kain. Ketika endek dan songket hanya dilihat sebagai objek transaksi, sebagai suvenir murah meriah bagi para pelancong, maka kita telah kehilangan esensi terdalamnya. Kita telah mereduksi kekayaan budaya menjadi sekadar komoditas yang bisa diproduksi tanpa hati dan tanpa akar. Tentu, kita tak bisa menolak zaman. Namun, kita punya pilihan untuk menentukan arahnya. Ajakan untuk mencintai dan membeli produk asli Bali bukan sekadar sentimen kedaerahan, melainkan upaya untuk menjaga nyala api tradisi agar tak benar-benar padam. Kita perlu merayakan keunikan, menghargai proses yang penuh kesabaran, dan memberikan ruang bagi para pengrajin untuk terus berkarya dengan kebanggaan. Selembar kain memang tampak sederhana. Namun, di dalamnya terjalin benang-benang sejarah, seni, dan identitas. Jika kita biarkan ia terkoyak oleh arus imitasi dan plagiarisme, maka kita bukan hanya kehilangan selembar kain, tetapi juga sebagian dari jiwa kita sendiri. Bali, yang kita kenal dengan keindahan dan keadiluhungannya, layak mendapatkan lebih dari sekadar suvenir murahan. Ia layak mendapatkan penghargaan atas setiap helai benang yang ditenun dengan cinta dan dedikasi. Inilah saatnya kita merajut kembali makna yang mulai pudar, sebelum semuanya benar-benar hilang ditelan riuhnya zaman. (*) (Argus Darshan)
Baca juga:
Bebal











.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)