Padi, Plastik, dan Pengakuan
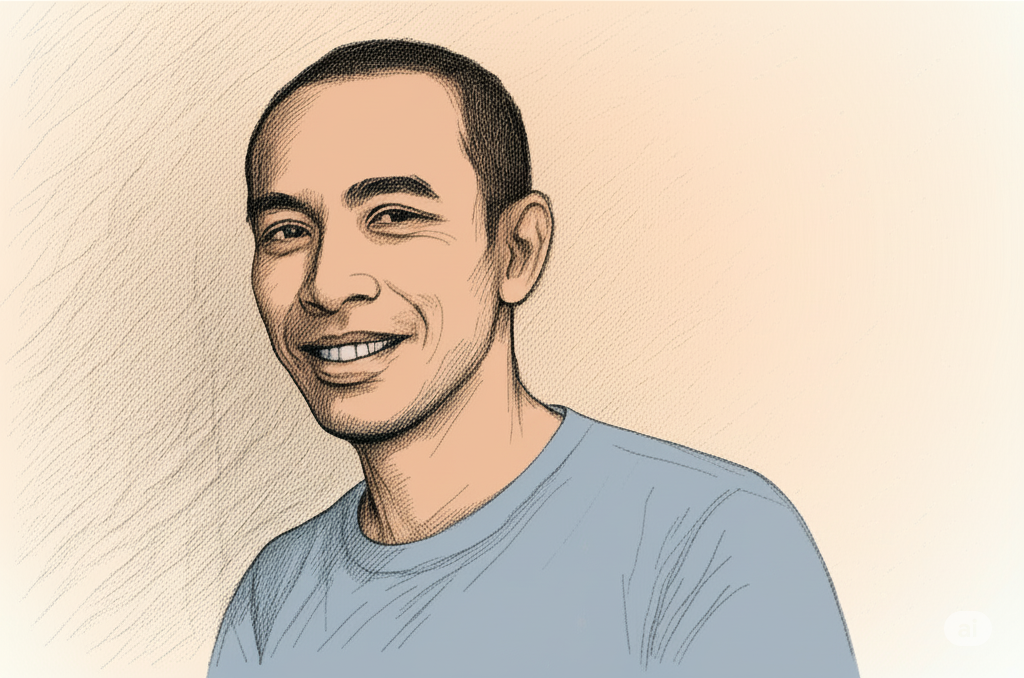
PAGI turun pelan di antara sisa kabut dan bayang sawah yang mulai mengering. Di dapur, air hampir mendidih, aroma kopi mengendap tanpa suara. Tapi pandangan ke luar jendela membawa getir yang tak bisa diredam gula. Di petak sawah yang dulu menghijau, berdiri spanduk besar bertuliskan: “Tanah Ini Segera Dibangun.”
Dulu, di tanah yang sama, petani menanam padi dengan rasa, bukan sekadar skema. Tangan mereka tahu kapan menanam, kapan menunggu hujan, kapan memberi doa. Tapi sekarang, suara burung sawah digantikan raungan mesin, dan air irigasi dialihkan ke kolam pribadi. Di atas lumpur yang dulu subur, mengalir sisa semen dan plastik dari proyek vila.
Subak—sistem irigasi yang mengatur lebih dari sekadar aliran air—kini hanya jadi nama yang dicantumkan dalam dokumen perizinan. Nilainya dipakai sebagai jualan budaya, tapi maknanya dibiarkan layu. Petani menjadi penonton di tanah sendiri. Padi dianggap tak produktif jika tak bisa dihitung dalam mata uang asing.
“Pembangunan tak boleh dimaknai sebagai penghapusan tradisi demi efisiensi. Sebab dalam setiap adat, terkandung nalar ekologis yang belum tentu bisa digantikan teknologi.”
— Michel Serres, The Natural Contract
Di brosur properti, kata-kata seperti eco-living, green concept, dan Bali experience dicetak tebal. Tapi sawah yang dijanjikan dalam visual, hanyalah latar. Di restoran mewah, nasi disajikan dalam mangkuk bambu, sementara petani yang menanamnya menjadi tukang parkir di halaman belakang.
Anak-anak muda mulai menjauh dari pertanian. Bukan karena malas, tapi karena tak dihargai. Mereka tak melihat harga diri dari lumpur, hanya dari seragam, Wi-Fi, dan pendingin ruangan. Padahal dulu, kakek mereka membungkuk di ladang bukan karena rendah—tapi karena menghormati tanah.
Kita terlalu mudah memoles citra Bali untuk dunia luar, tapi lupa mencintainya dari dalam. Kita mengemas keaslian menjadi konten, tapi tidak lagi merawat yang asli. Kita lupa bahwa padi bukan hanya makanan, tapi cara hidup. Dan plastik bukan hanya limbah, tapi tanda bahwa kita mulai terbiasa membuang.
“Kita tak hanya kehilangan padi, tapi kehilangan cara untuk mengucapkan terima kasih pada tanah.”
— Wendell Berry, The Unsettling of America
Air sudah berhenti mendidih. Kopi tinggal ampas. Di luar, petak-petak sawah makin kecil, makin sunyi. Tapi dari satu sudut, masih terlihat seorang petani menunduk, menanam dengan gerak yang sama seperti dulu. Mungkin ia tahu, bahwa tanah tak butuh banyak kata. Ia hanya butuh diakui dan tidak dilupakan.
Dan pengakuan itu seharusnya lebih dari sekadar plakat atau piagam. Ia harus hadir dalam ruang hidup, dalam kebijakan, dan dalam keberanian untuk berkata: Pembangunan yang melukai petani, bukan kemajuan. Itu kehilangan arah. (*)
Menot Sukadana
Pernah muda, masih ngopi, belum pensiun dari mikir.










