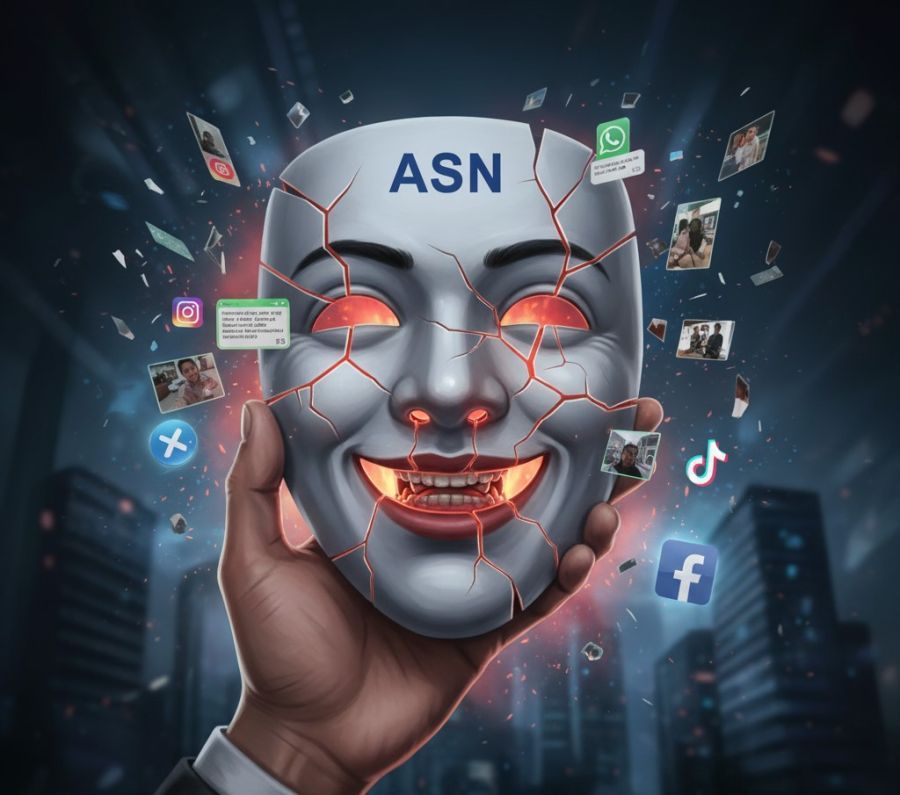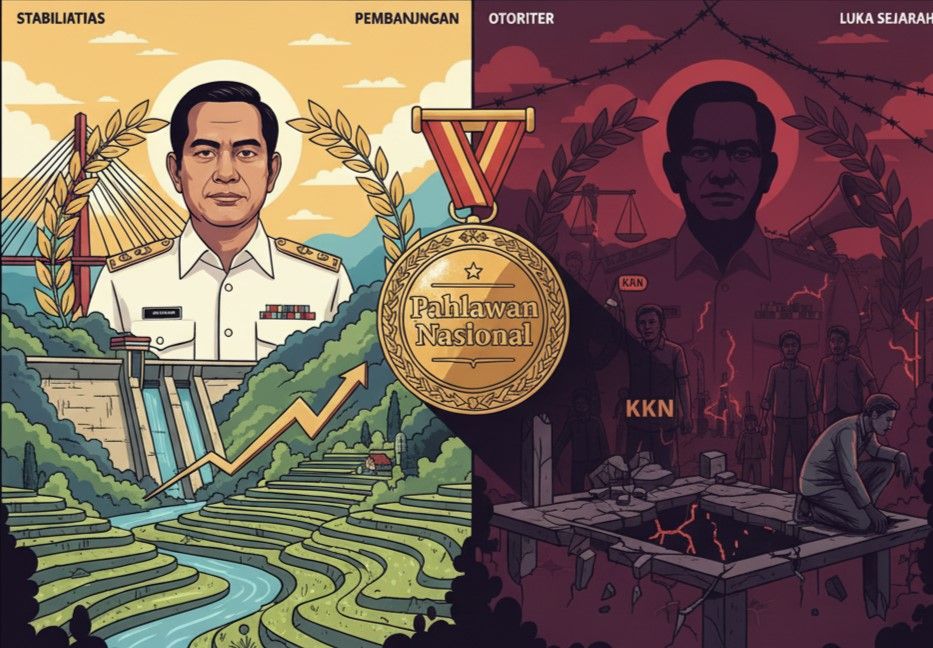Perintis? Ah kita semua pewaris..!
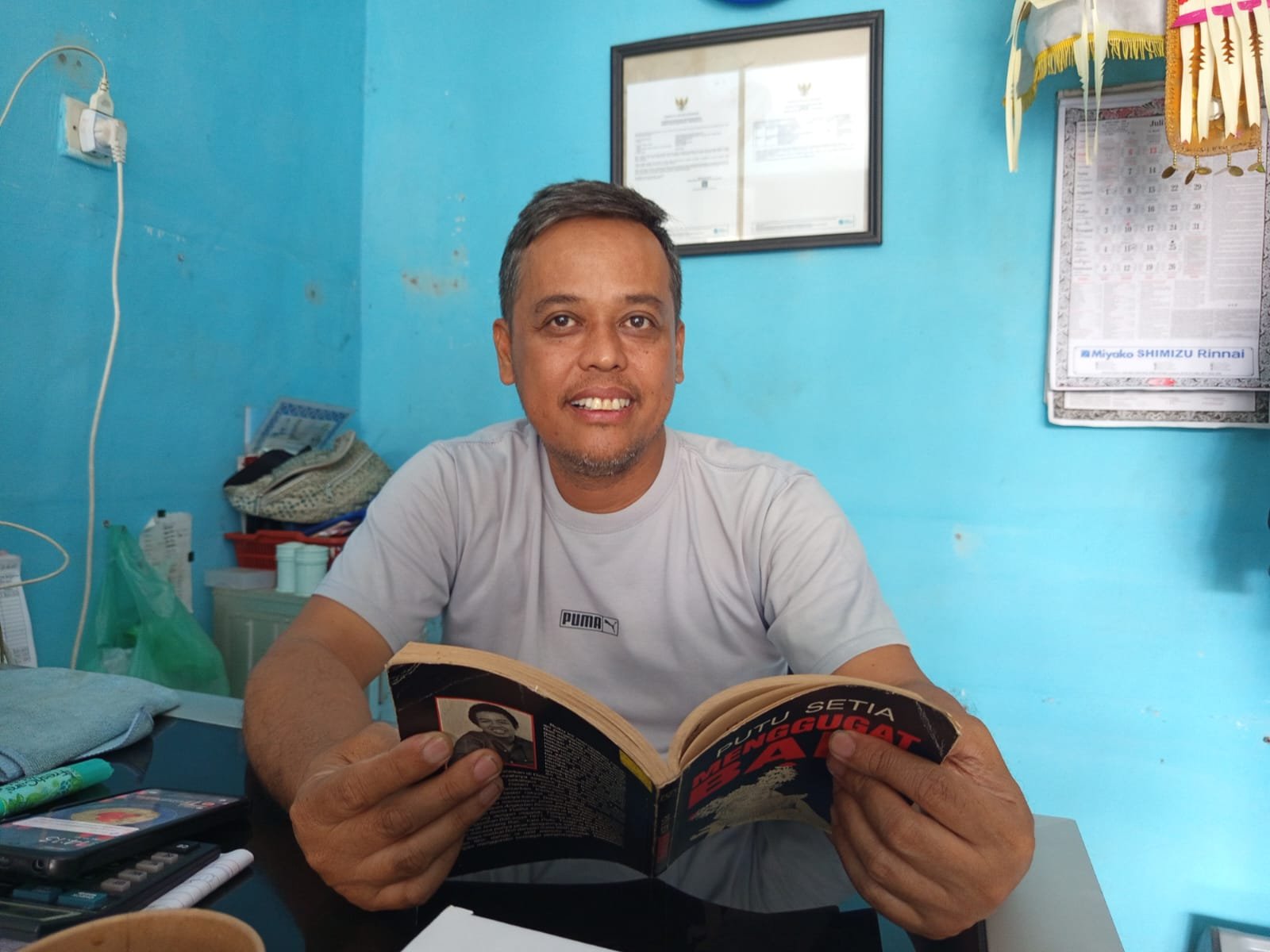
Menelusuri Jejak Identitas Budaya di Balik Nama keluarga, Darah, dan Warisan Psikologis.
PADA komunitas-komunitas desa di Bali, adalah jamak seorang pria dipanggil dengan menyisipkan nama anaknya, misalnya Pan Karma. Karma bukan namanya, anaknyalah yang bernama Karma.
Tak seorang pun menyebut namanya sendiri. Dan itu bukan karena orang lupa — tapi karena nama anaknyalah kini yang jadi penanda keberadaannya setelah ia tua.
Di sisi lain desa, seorang perempuan tua dikenal sebagai Men Luh, ibunya I Luh.
Orang-orang menyapanya dengan lembut, penuh hormat. Tapi tetap saja, ia lebih dikenal karena anaknya, bukan dirinya.
Dan rupanya, hal serupa tak hanya terjadi di Bali. Di banyak sudut budaya Indonesia, identitas pribadi larut dalam relasi darah dan silsilah.
Di Jawa, “anaknya Bu Narti.”
Di Minang, “keponakan Pak Datuk.”
Di Toraja, “dari keluarga Rante Tondok.”
Nama pribadi menyusut, sementara nama keluarga membesar.
Ketika Nama Jadi Peta Sosial
Dalam budaya komunal dan agraris seperti yang tumbuh di desa-desa Nusantara, individu bukanlah pusat.
Yang utama adalah keluarga, komunitas, dan sejarah sosial. Maka, menyebut seseorang bukan sebagai “aku” tapi sebagai “anak siapa” atau " Keluarga siapa " Itu adalah cara masyarakat menjaga peta sosial tetap diingat dan dijaga.
Di desa-desa di Bali jamak orang tua bertanya pada yang lebih muda ; " Nyen ngelah nak cenik? " , “Kamu anaknya siapa?”
Maka dijawab :
“ Panak ne Pak Made guru SD.”, “Anaknya Pak Made yang guru SD. Atau“Cucune Jro Mangku Dalem uli Banjar Tengah.”, “Cucu Jro Mangku Dalem dari Banjar Tengah.
Di balik pernyataan itu, terselip sistem nilai, yaitu, siapa kamu, dari mana kamu berasal, dan harapan apa yang melekat padamu. Nama bukan hanya soal nama belaka, tapi soal posisi — dalam peta sosial, dalam struktur keluarga, dan dalam sejarah keluarga dan komunitas.
Warisan Tak Selalu Berupa Harta
Dalam pengamatan yang lebih dalam, nama bukan satu-satunya yang diwariskan. Sifat pun diwariskan, harapan diturunkan, luka disisipkan diam-diam ke generasi berikutnya.
Seorang anak bisa dicap “pemalu seperti ayahnya”. Atau “keras kepala seperti neneknya dulu.” Bahkan jejak itu masih bisa ditelusuri sampai kumpi dan buyut.
Dan tanpa sadar, seorang anak tumbuh dengan ‘naskah’ yang telah ditulis untuknya jauh sebelum ia bisa berkata ‘aku’.
Ia jadi pewaris — bukan hanya rumah dan ladang, tapi juga trauma yang belum selesai, ambisi yang tak tuntas, dan reputasi yang belum pulih.
Psikologi di Balik Nama
Dalam teori psikologi keluarga dari Bowen, ini disebut sebagai family projection process.
Sistem ini menjelaskan bagaimana orang tua — seringkali tanpa sadar — mentransfer harapan, ketakutan, dan masalah emosionalnya kepada anak.
Contohnya, seorang anak yang dipaksa menjadi dokter, karena kakeknya gagal jadi mahasiswa kedokteran. Atau, seorang kakak yang selalu dianggap “kurang berbakat”, karena adiknya lebih mirip ayahnya yang dulu juara kelas.
Identitas anak dibentuk bukan dari dalam dirinya, tapi dari bayangan tentang siapa dan bagaimana seharusnya dia menjadi.
Maka, dalam masyarakat yang penuh simbol dan tradisi, perjalanan menjadi diri sendiri sering dimulai dengan harus melepaskan cerita lama.
Antara Akar dan Sayap
Tentu, sistem sepert ini mempunya sisi indah dan positif, yakni menciptakan rasa aman, akar, dan kesinambungan.
Seorang anak menjadi tahu dan paham dari mana ia berasal. Ia merasa terhubung dengan leluhurnya, dengan kampung halamannya, dengan sejarahnya.
Namu, akar yang terlalu kuat juga bisa menjadi semacam rantai. Identitas komunal yang terlalu tebal bisa membelenggu.
“Aku ingin menjadi diriku sendiri”, Itulah pernyataan yang sering muncul — dan semakin relevan di tengah masyarakat modern yang mulai menggugat narasi lama.
Menulis Ulang Warisan
Mungkin, seperti kata para psikolog humanistik, setiap manusia pada akhirnya perlu menulis ulang ceritanya sendiri. Bukan untuk memutus warisan, tapi untuk memurnikannya. Juga, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memahaminya dengan lebih baik.
Bahwa tidak semua cerita yang diwariskan harus dilanjutkan dengan apa adanya.
Kita bisa menghormati nama keluarga — tapi juga bisa memilih arah sendiri. Kita bisa mengenang ayah atau ibu — tanpa harus hidup sebagai ‘salinan’ dari mereka.
Dan pada titik itu, kita belajar bahwa identitas bukan hanya apa yang diwariskan, tapi juga apa yang kita bangun sendiri.
Dalam Nama, Tersimpan Dunia
Di balik nama-nama yang kita warisi — Pan Wayan, Men Luh, anaknya Pak Umar, cucunya Bu Narti — tersembunyi dunia rumit, dunia sosial, sistem nilai, dan beban psikologis yang jarang disadari.
Sebagai bangsa yang hidup dalam budaya relasi dan silsilah, ketika ada seorang anak yang berbeda — menempuh jalan tak biasa, memilih keyakinan sendiri, atau sekadar "tidak mirip siapa-siapa" — jangan buru-buru berkata: “Nyen kaden numadi? Nak sing ada nu kekene di keluarge rage.”, “Siapa sih yang menitis (lahir kembali, reinkarnasi), sebab tak ada yang seperti ini di keluarga kita”.
Kalimat seperti itu bukan sekadar sindiran. Itu beban tak kasat mata yang bisa membekas seumur hidup. Zaman berubah. Dunia makin kompleks. Hari ini, kita mungkin bukan perintis dalam arti tradisional.
Tapi kita adalah generasi yang dituntut berdamai dengan warisan, sambil berani menulis ulang babak kehidupan berikutnya. (*)
Oleh: I Made Indah Gunawan Saputra
Penulis adalah seorang wirausahawan asal Jembrana, Bali, tinggal di Kuta Selatan, Badung. Alumnus Program Studi Sosiologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka.