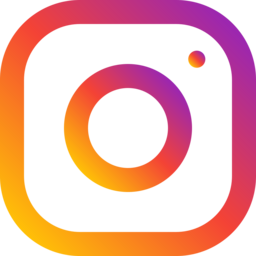Merawat Sungai, Menjaga Kota
 Nyoman Sukadana |
21 September 2025 | 22:41:00 WITA
Nyoman Sukadana |
21 September 2025 | 22:41:00 WITA

BANJIR yang melanda Denpasar pada pekan lalu meninggalkan sisa lumpur, sampah plastik, serta puing di sepanjang aliran Tukad Badung. Sungai yang sejatinya menjadi sumber kehidupan warga kota berubah menjadi ancaman ketika tidak dirawat dengan baik. Namun, dari peristiwa itu, lahir pula sikap yang menumbuhkan harapan: warga adat Desa Adat Denpasar secara serentak turun ke sungai untuk membersihkan bantaran. Sejak pagi, warga dari 60 banjar adat bergabung membawa cangkul, sabit, dan sapu. Mereka memungut plastik, mengangkat lumpur, dan menyingkirkan puing dengan bergotong royong. Aksi ini dipimpin langsung Bendesa Adat Denpasar, Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma, sekaligus bertepatan dengan peringatan World Clean Up Day. Pemkot Denpasar mendukung penuh dengan armada pengangkut sampah serta penyemprotan jalan oleh tim pemadam kebakaran. Inisiatif warga adat menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak hanya lahir dari kebijakan pemerintah, melainkan juga dari gerakan masyarakat. Gotong royong, yang sejak lama menjadi tradisi Bali, kembali menemukan relevansinya dalam menghadapi persoalan lingkungan perkotaan. Banjir bukan semata-mata akibat curah hujan, melainkan juga buah dari kelalaian kolektif: sampah yang dibuang ke sungai, penyempitan ruang terbuka hijau, serta alih fungsi lahan yang terus terjadi. Kebersihan Tukad Badung bukan hanya urusan estetika. Ia menyangkut keselamatan warga, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan kota. Sungai yang tersumbat sampah akan meluap setiap musim hujan, menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Karena itu, gotong royong warga adat hendaknya tidak dipandang sebagai kegiatan seremonial pascabanjir, melainkan sebagai langkah awal membangun budaya kolektif menjaga sungai. Pernyataan Bendesa Adat Denpasar bahwa bencana menjadi pengingat pentingnya kebersamaan layak dicatat. Nilai kebersamaan itulah yang menjadi modal sosial untuk menumbuhkan kesadaran ekologis. Jika kesadaran ini terpelihara, Denpasar dapat memiliki sistem perawatan lingkungan yang berjalan dari bawah, berawal dari banjar, diperkuat desa adat, dan didukung pemerintah kota. Pemkot Denpasar memiliki tanggung jawab memastikan gerakan ini tidak berhenti pada satu momentum. Aturan tegas soal pembuangan sampah, penyediaan sarana kebersihan, dan pengelolaan drainase ramah lingkungan harus dijalankan. Di sisi lain, desa adat melalui struktur banjar dapat menjadi penggerak kesadaran di tingkat komunitas. Kolaborasi keduanya akan menentukan apakah Tukad Badung kelak menjadi sungai yang bersih dan berdaya guna, atau sekadar tempat pembuangan yang menunggu bencana berikutnya. Langkah prajuru Desa Adat menyalurkan bantuan sembako serta santunan bagi warga terdampak adalah bentuk kepedulian sosial. Namun, perhatian yang lebih penting adalah upaya sistematis mencegah bencana serupa terulang. Banjir harus dipandang bukan sebagai peristiwa musiman, melainkan peringatan agar tata kelola kota lebih berpihak pada lingkungan. Editorial ini menekankan bahwa menjaga sungai sama artinya dengan menjaga kota. Tukad Badung adalah urat nadi Denpasar. Bila ia rusak, maka kehidupan kota pun terancam. Karena itu, gotong royong warga adat semestinya menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Denpasar untuk tidak lagi abai terhadap sungai. Bencana memang meninggalkan luka, tetapi dari luka itu lahir kesadaran baru. Tugas semua pihak kini adalah memastikan kesadaran itu tidak cepat hilang. Sungai harus dirawat, bukan hanya ketika banjir usai, melainkan setiap hari sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif warga kota. Dengan demikian, Denpasar dapat tumbuh sebagai kota yang tidak hanya modern, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. (*)
Baca juga :
• Bali Melawan Rabies
• Perpres untuk MBG
• Tumpek Landep dan Sungai yang Kotor