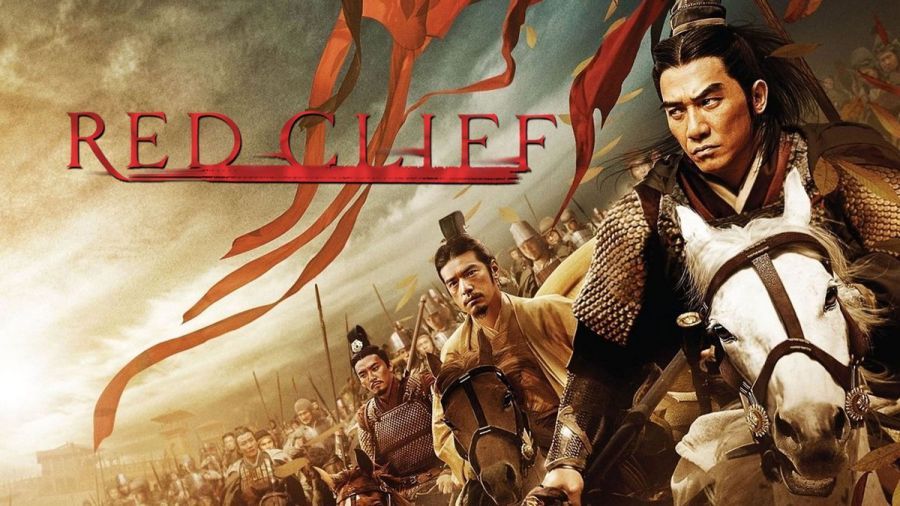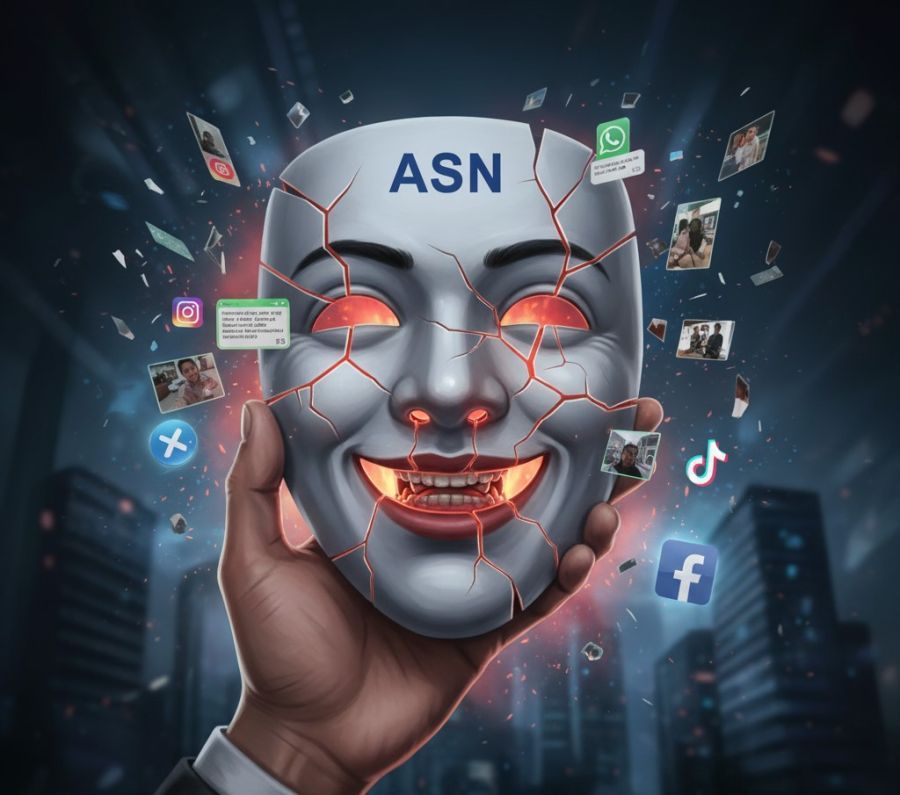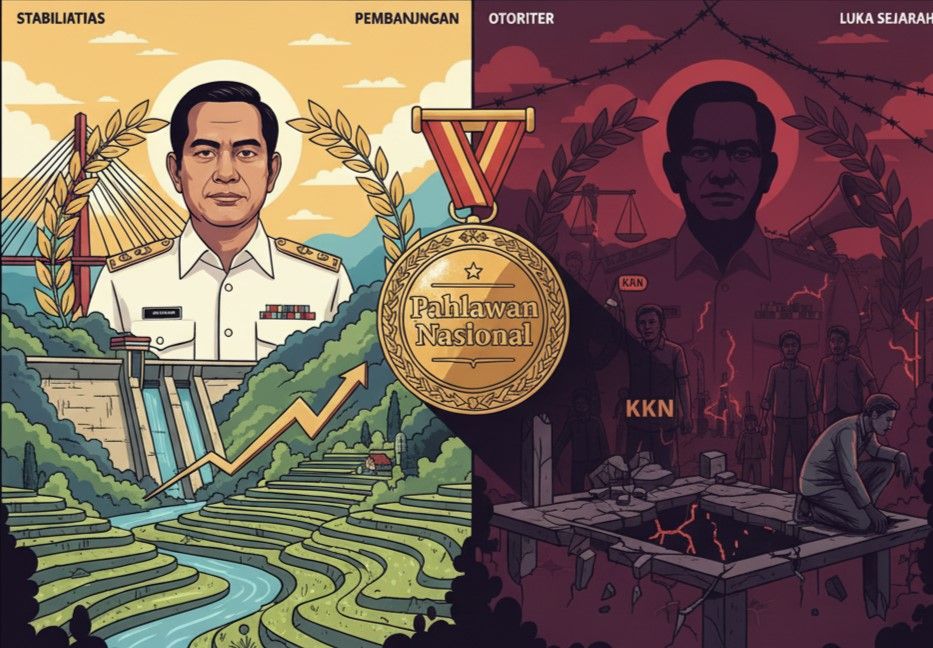Dilema Bali Antara Otsus dan Kewenangan Khusus

Analisis Pergulatan Hukum Melindungi Budaya dan Ekonomi
WACANA Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Bali telah menjadi pembahasan yang berulang dan muncul sejak tahun 1999, atau selama lebih dari dua dekade. Isu ini lahir dari kesadaran mendalam akan keunikan budaya, sistem adat, dan peran vital Bali sebagai sumber devisa utama negara. Namun, perdebatan kini mengerucut pada satu pertanyaan mendasar: Apakah Bali butuh status Otsus formal seperti Aceh dan Papua, atau cukup dengan kewenangan khusus yang diakui undang-undang?
Pergulatan ini menempatkan Bali pada persimpangan antara identitas tradisional yang ingin dipertahankan dan tuntutan modernitas yang terus mengancam kelestariannya. Aspirasi Otsus tidak hanya menyentuh aspek politik, tetapi juga jantung ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya pulau tersebut.
Latar Belakang Historis Otsus Bali
Wacana kekhususan Bali bermula pada era Reformasi seiring disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberi otonomi yang luas namun bersifat seragam untuk semua daerah. Bali merasa sistem otonomi yang seragam tersebut gagal mengakomodasi struktur sosial, budaya, dan adatnya yang unik, khususnya lembaga Desa Adat (Desa Pakraman) dan sistem irigasi filosofis Subak.
Gelombang tuntutan untuk status istimewa semakin menguat pada periode awal tahun 2000-an. Para tokoh adat, akademisi, dan politisi mulai menyuarakan perlunya payung hukum yang kuat untuk melindungi jati diri Bali dari dampak pariwisata masif, eksploitasi lahan, dan kerusakan lingkungan yang tidak sebanding dengan pembagian hasil yang diterima daerah.
Puncak kesadaran ini terjadi pasca Tragedi Bom Bali I tahun 2002. Peristiwa itu menyadarkan banyak pihak bahwa budaya dan keamanan tradisional Bali bukan hanya aset pariwisata, tetapi juga benteng ketahanan sosial dan ekonomi nasional.
Sejak saat itu, upaya untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali yang memuat kekhususan terus digulirkan. Pada periode 2005 hingga 2015, pembahasan RUU Otsus ini sempat mengalami stagnasi karena tarik ulur politik dan ketidakjelasan model kekhususan yang akan diusung. Akhirnya, wacana Otsus penuh bergeser menjadi Otonomi Asimetris atau pemberian Kewenangan Khusus yang terfokus.
Status Hukum Asimetris
Pakar hukum tata negara terkemuka, Jimly Asshiddiqie, sering menyoroti konsep Otonomi Asimetris sebagai solusi yang paling masuk akal bagi daerah-daerah dengan kekhususan unik. Konsep ini sangat relevan bagi Bali karena kekhususannya bukan terletak pada Sumber Daya Alam (SDA) migas atau tambang, melainkan pada kekuatan kulturalnya yang menjadi modal utama pariwisata dunia.
Otsus Bali, menurut pandangan ini, harusnya berbentuk pengakuan kewenangan yang mendalam terhadap Desa Adat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, alih-alih pada kewenangan administratif biasa.
Jimly berpendapat, Bali harus punya otoritas membuat regulasi ketat, bahkan jika bertentangan dengan UU Nasional yang umum, demi menjaga kelestarian budaya dan lingkungan yang menjadi modal utamanya. Tujuannya bukan sekadar otonomi politik, melainkan pencapaian otonomi kultural dan ekologis yang memungkinkan Bali mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan filsafat hidup Tri Hita Karana.
Kegagalan menerapkan otonomi yang disesuaikan ini dikhawatirkan akan menyebabkan kehancuran masal dari tatanan adat yang tidak mampu bersaing dengan laju pembangunan kapitalis.
Menguatkan Posisi Adat
I Dewa Gede Palguna, Ahli Hukum Tata Negara dan Mantan Hakim Konstitusi, dalam berbagai kesempatan, telah menekankan bahwa keunikan Bali terletak pada integrasi tak terpisahkan antara budaya, agama, dan adat. Palguna berpendapat bahwa Otsus diperlukan untuk memposisikan Desa Adat sebagai subjek hukum otonom yang kuat, bukan sekadar objek pembangunan.
Tanpa Otsus yang kuat, Desa Adat rentan tergilas oleh kepentingan investasi dan birokrasi, yang seringkali mengabaikan kearifan lokal seperti fungsi Subak sebagai sistem irigasi sekaligus manifestasi filosofi hidup.
Palguna melihat Otsus sebagai payung hukum terkuat untuk memberikan Desa Adat kewenangan fiskal (mengelola dana) dan kewenangan regulasi (membuat awig-awig atau peraturan adat) yang berdampak langsung pada tata ruang dan kehidupan sosial.
Penguatan ini vital agar pembangunan yang berjalan tidak merusak tatanan adat yang telah berusia ratusan tahun, yang pada akhirnya akan meruntuhkan daya tarik pariwisata Bali itu sendiri. Ini merupakan upaya perlindungan total terhadap eksistensi Bali.
Kebutuhan Dana Non-SDA
Dari sisi ekonomi, Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi model pembagian hasil yang ada. Meskipun Bali menyumbang devisa besar dari pariwisata, porsi anggaran yang diterima dinilai tidak adil dan tidak sebanding dengan biaya kerusakan lingkungan yang harus ditanggung.
Basri berargumen bahwa Bali memerlukan skema dana khusus non-SDA yang unik. Karena Bali tidak memiliki SDA berupa migas, dana Otsus harusnya didasarkan pada persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa pariwisata, seperti Pajak Hotel dan Restoran (PHR) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pariwisata yang ditarik pemerintah pusat.
Dengan Otsus, Bali bisa bernegosiasi untuk mendapatkan porsi yang jauh lebih besar dari sektor ini. Dana ini kemudian wajib dialokasikan langsung bagi pembangunan infrastruktur budaya dan lingkungan, sekaligus menyeimbangkan pembangunan antara wilayah selatan yang kaya dan wilayah utara atau timur yang masih tertinggal.
Inilah kunci untuk mengatasi kesenjangan internal di Bali dan meminimalisir kecemburuan sosial.
Kompromi UU Provinsi 2023
Wacana Otsus penuh menemui titik kompromi melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. UU ini secara eksplisit mengakui dan memberikan penguatan terhadap keistimewaan Bali, Desa Adat, dan Subak, serta menjadi pengganti UU lama yang telah usang. Meskipun Gubernur Bali saat ini secara formal menolak status Otsus murni, UU 15/2023 adalah langkah konkret menuju Otonomi Asimetris versi Bali.
Namun, bagi sebagian kalangan, kompromi ini masih dianggap "otonomi biasa dengan branding khas Bali," karena tidak memberikan keleluasaan fiskal dan regulasi yang radikal seperti yang dituntut para pendukung Otsus sejati. Mereka berpendapat, selama Bali tidak memiliki kewenangan penuh atas dana pariwisata dan tidak bisa membuat regulasi tata ruang yang mutlak, ancaman betonasi dan degradasi lingkungan yang berujung pada masalah seperti banjir Denpasar akan terus ada.
Perbedaan Kunci Otsus
Perdebatan Otsus Bali menjadi unik karena berbeda dari implementasi di Aceh dan Papua. Aceh mendapatkan Otsus berbasis konflik dan kekayaan SDA, sedangkan Papua berbasis ketertinggalan dan SDA. Bali, sebaliknya, mengajukan Otsus berbasis Budaya dan Pariwisata sebagai aset nasional.
Kesulitan utama bagi Bali adalah tidak adanya "cantolan hukum" yang jelas untuk mendapatkan dana Otsus yang besar, karena pendapatan utama Bali berasal dari investasi dan jasa, bukan dari SDA yang secara tradisional diatur oleh negara.
Inilah yang membuat perjuangan Bali lebih mengarah pada penguatan regulasi dan kewenangan, bukan skema dana Otsus yang masif, yang secara politis lebih sulit dicapai.
Pada akhirnya, UU Nomor 15 Tahun 2023 adalah kompromi politik yang mengakui kekhususan Bali. Meskipun status Otsus secara formal tidak disandang, dorongan untuk mendapatkan kewenangan khusus tetap tinggi. Bali kini ditantang untuk membuktikan bahwa kewenangan baru dalam UU tersebut cukup kuat untuk menertibkan tata ruang, melindungi adat, dan mengelola pariwisata secara berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa pembangunan fisik tidak menggerus warisan budaya demi tujuan ekonomi semata.(*)
Menot Sukadana