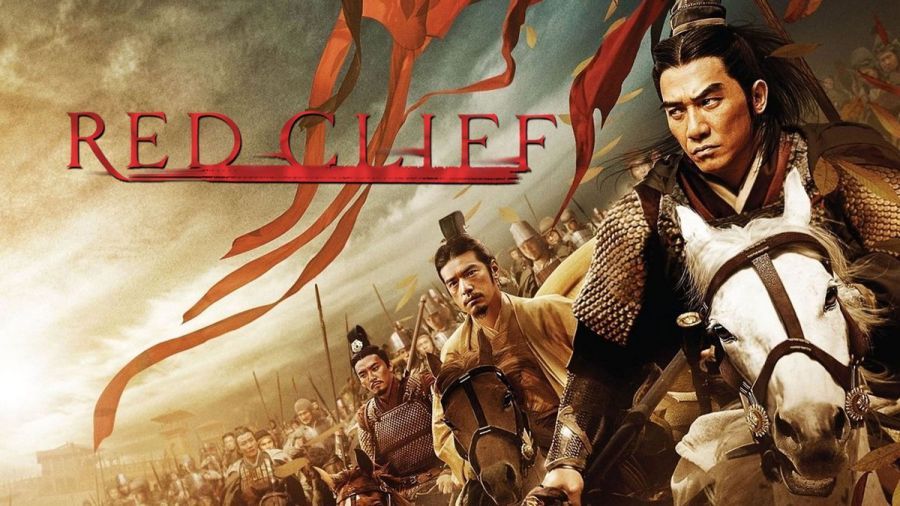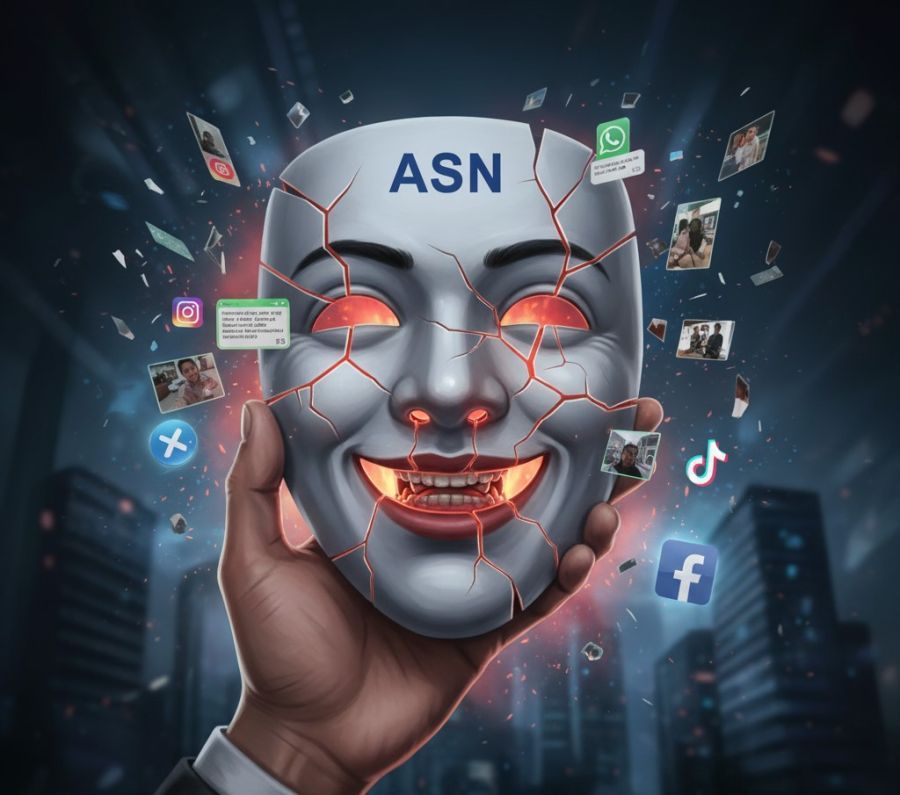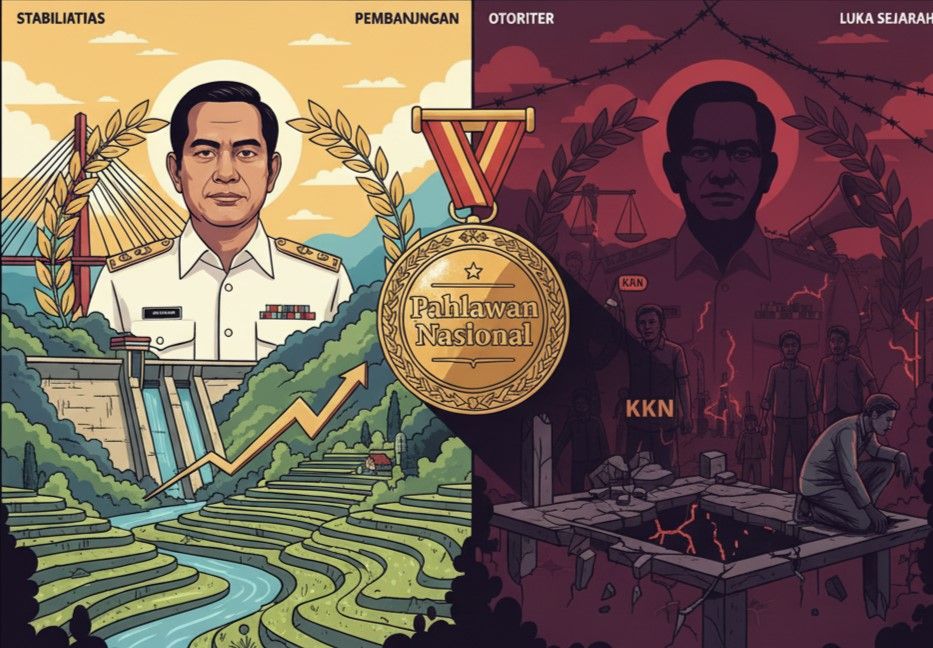Sarbagita: Metropolitan Bali Terancam Kehilangan Jati Diri

KAWASAN Bali Selatan yang mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan, atau yang diakronimkan sebagai Sarbagita, kini telah mencapai status sebagai Kawasan Metropolitan. Penetapan ini bukan hanya klaim, melainkan pengakuan resmi yang diatur dalam kerangka hukum nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita, menetapkannya sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Dasar hukum ini menandai titik balik perencanaan di Bali, di mana pembangunan tidak lagi dapat diselesaikan hanya pada batas administratif kota atau kabupaten, melainkan harus dikoordinasikan secara sistemik dalam skala regional.
Data demografi menunjukkan bahwa populasi fungsional di wilayah inti Sarbagita telah melampaui 1,77 juta jiwa, sebuah angka yang secara tegas memenuhi kriteria kuantitatif sebuah kota raya di Indonesia. Populasi ini terbagi secara fungsional: Denpasar sebagai Kota Inti, adalah pusat administrasi pemerintahan, pendidikan, dan jasa utama. Badung, dengan kawasan-kawasan primadona seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu, menjadi episentrum ekonomi pariwisata dan penyerap modal terbesar. Sementara itu, Gianyar dan Tabanan berfungsi sebagai kawasan penyangga hunian utama, menampung ribuan komuter harian. Pergerakan komuter yang masif dan lintas batas administrasi inilah yang menjadi bukti empiris dari integrasi fungsional metropolitan.
Namun, di balik status prestisius dan kontribusi ekonominya yang besar, Sarbagita menghadapi dilema pembangunan yang serius. Pertumbuhan metropolitan didominasi oleh logika pasar dan modal pariwisata, sebuah pola yang menurut tinjauan teori merupakan ciri khas Urbanisasi Neoliberal (David Harvey). Hal ini menciptakan sebuah ironi yang mendalam: daerah yang seharusnya menjadi etalase pariwisata budaya justru menderita krisis ekologis dan terancam kehilangan identitas kulturalnya, menempatkan filosofi Tri Hita Karana dalam bahaya.
Konflik Ruang
Isu paling mendesak yang dihadapi Sarbagita adalah krisis fisik yang terwujud dalam Urban Sprawl, di mana pembangunan properti dan akomodasi wisata meluas secara tidak terkendali dari pusat Badung dan Denpasar menuju wilayah penyangga di Gianyar dan Tabanan. Lensa teori Urbanisasi Neoliberal menunjukkan bahwa pola pembangunan ini didorong oleh spekulasi lahan dan akumulasi modal. Akibatnya, alih fungsi lahan terjadi secara masif, terutama mengancam sistem Subak.
Data menunjukkan betapa cepatnya ancaman ini terjadi: di Kabupaten Badung, laju alih fungsi lahan sawah mencapai rata-rata sekitar 384,14 hektar per tahun, sementara Denpasar mencatat penurunan sekitar 49 hektar per tahun. Laju konversi yang masif ini telah menyebabkan hilangnya ribuan hektar lahan Subak. Lahan Subak, sebagai warisan budaya dunia, berfungsi vital sebagai daerah resapan air. Ketika digantikan beton, kapasitas penyerapan air menghilang, berkontribusi pada krisis air dan memperburuk banjir di musim hujan.
Krisis ini diperparah oleh krisis transportasi yang melumpuhkan. Dengan total populasi kendaraan bermotor di Bali yang telah melampaui lima juta unit, dengan konsentrasi tertinggi berada di Denpasar dan Badung, kemacetan kronis di koridor-koridor utama adalah keniscayaan. Pertumbuhan kendaraan yang tak terkendali ini jauh melampaui kapasitas ruas jalan, menjadikan perjalanan harian bagi jutaan komuter sebagai beban yang sangat berat.
Krisis Ekologis
Secara ekologis, Sarbagita telah melampaui batas Daya Dukung Lingkungan (Carrying Capacity). Konsep ini sangat relevan untuk menjelaskan mengapa infrastruktur dasar di kawasan metropolitan ini kolaps. Beban dari populasi fungsional yang tinggi, ditambah volume wisatawan, telah menempatkan tekanan berat pada sumber daya kritis, yakni lahan Subak dan air baku.
Krisis sampah adalah salah satu indikator paling mencolok. Total produksi sampah harian di Bali diperkirakan mencapai sekitar 4.281 ton per hari, dengan Sarbagita (Denpasar dan Badung) menyumbang lebih dari 2.000 ton per hari. Volume sampah yang masif ini telah menyebabkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung kelebihan kapasitas. Selain sampah, air baku juga terancam. Kebutuhan air bersih tahunan untuk Sarbagita telah diperkirakan mencapai sekitar 4.936,33 liter per detik pada tahun 2020. Hilangnya lahan resapan dan tingginya penggunaan air oleh sektor pariwisata memicu kekhawatiran serius akan krisis air dalam dua dekade mendatang. Krisis lingkungan ini termanifestasi pula dalam peningkatan kasus banjir tahunan di kawasan padat seperti Kuta dan sepanjang By Pass Ngurah Rai, akibat buruknya sistem drainase.
Krisis Budaya
Di tengah krisis fisik ini, Sarbagita menghadapi ancaman paling serius terhadap jati dirinya, yang dapat dianalisis melalui teori Komodifikasi Budaya. Budaya Bali, dengan ritual, pura, dan keseniannya, berisiko direduksi menjadi komoditas untuk dijual kepada pasar turis. Fenomena ini diperkuat oleh teori The Tourist Gaze (pandangan wisatawan John Urry), yang cenderung melihat Bali sebagai fantasi yang dapat dieksploitasi.
Akibatnya, nilai-nilai spiritual pura dan ritual dihadapkan pada kepentingan komersial, mengikis makna Niskala. Perilaku minoritas wisatawan asing yang melanggar etika dan hukum di tempat suci atau ruang publik telah memicu konflik sosial, menunjukkan bahwa kedaulatan budaya dan hukum lokal terancam. Hal ini menggarisbawahi urgensi untuk melindungi aspek Parihyangan dan Pawongan dalam pembangunan metropolitan.
Perencanaan Berbasis Tri Hita Karana
Untuk menyelamatkan jiwa Bali dalam kerangka metropolitan, dibutuhkan pergeseran paradigma perencanaan yang fundamental. Status KSN Sarbagita harus diikuti oleh tanggung jawab nasional untuk mengintegrasikan filosofi Tri Hita Karana sebagai kerangka regulasi pembangunan.
Solusi strategis harus komprehensif. Pertama, reformasi transportasi harus didorong melalui pembangunan sistem Transportasi Publik Masal yang andal, seperti e-BRT terintegrasi. Kedua, penyelesaian krisis lingkungan melalui transisi dari TPA ke model TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang tersebar. Ketiga, perlindungan lahan dan budaya harus menjadi prioritas tertinggi. Pemerintah harus menetapkan Batas Tegas (Hard Boundary) pada wilayah Subak dan memberikan insentif finansial bagi petani yang mempertahankan lahan produktif, demi menjaga fungsi ekologisnya (Palemahan). Di sisi budaya, diperlukan regulasi tegas terhadap perilaku wisatawan dan penguatan Zona Sakral (Parihyangan) di sekitar pura, memastikan bahwa nilai budaya selalu menjadi filter utama pembangunan.
Terakhir, dibutuhkan penguatan Tata Kelola. Dibutuhkan Badan Pengelola KSN Sarbagita yang kuat, yang mampu menyinkronkan anggaran dan kebijakan lintas batas administrasi Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Hanya melalui intervensi radikal yang mengintegrasikan semua pilar ini, Sarbagita dapat membuktikan kepada dunia bahwa pembangunan metropolitan dapat berjalan serasi tanpa mengorbankan spiritualitas dan keunikan yang menjadi daya tarik utamanya. (*)
Menot Sukadana