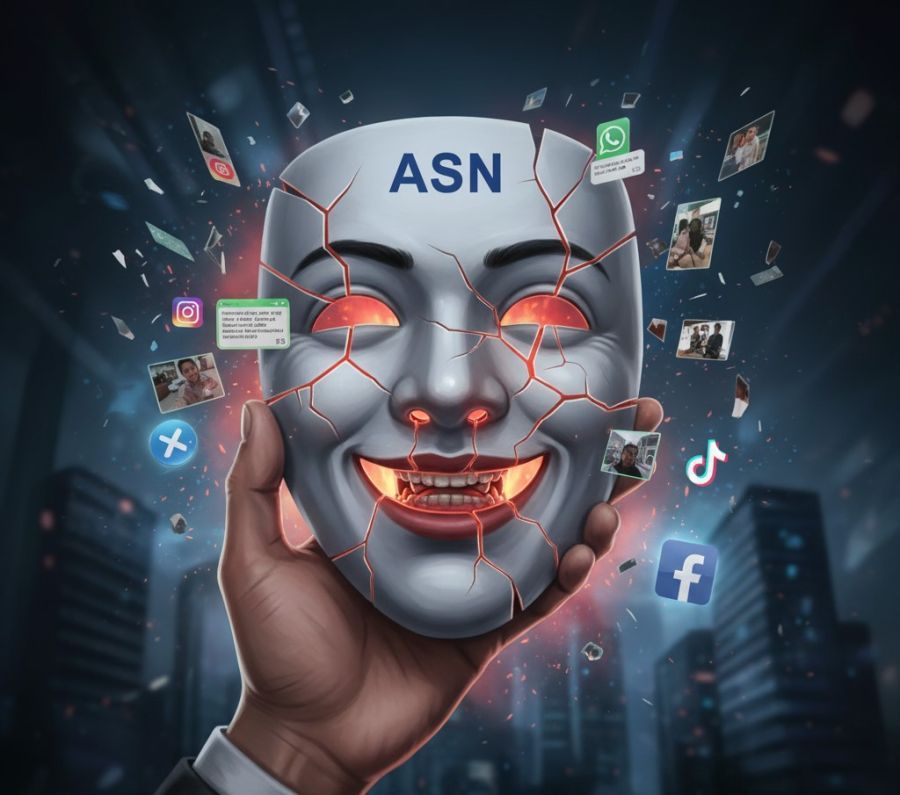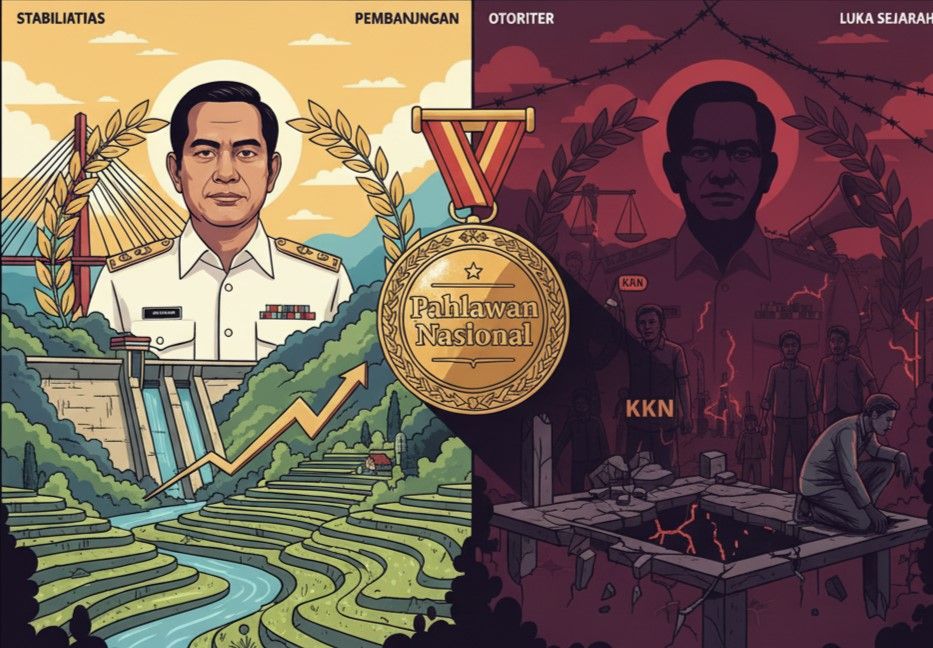Pendidikan di Tengah Banjir

BANJIR besar yang melanda Bali pada 9 September 2025 adalah tragedi yang menyentuh banyak sisi kehidupan masyarakat. Tidak hanya merenggut korban jiwa, menghancurkan rumah, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi, tetapi juga merusak salah satu fondasi terpenting masa depan: pendidikan. Data mencatat 1.835 sekolah terdampak, dengan 60 sekolah mengalami rusak berat. Lebih dari 900 siswa dan puluhan guru harus merasakan langsung bagaimana ruang belajar yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman, kini berubah menjadi lokasi darurat yang penuh lumpur dan trauma.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka, ada wajah anak-anak yang kehilangan ruang belajarnya. Ada guru yang kebingungan melanjutkan proses pembelajaran. Ada orang tua yang resah melihat masa depan anak mereka tertunda oleh bencana. Banjir kali ini menjadi teguran nyata bahwa pendidikan, yang selama ini sering dianggap berjalan apa adanya, sebenarnya rapuh ketika berhadapan dengan bencana alam.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan komitmen untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana sekolah pada tahun anggaran 2026. Komitmen itu patut diapresiasi, namun juga perlu dilihat dengan kacamata kritis. Tahun 2026 berarti masih ada jeda satu tahun penuh sebelum perbaikan bisa benar-benar dirasakan. Sementara itu, hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan tidak bisa menunggu.
Tidak cukup hanya mengandalkan janji bantuan jangka panjang, pemerintah daerah harus segera menyiapkan solusi sementara agar proses belajar tetap berjalan. Menggunakan fasilitas darurat, membuka ruang kelas sementara di balai banjar, pura, atau gedung-gedung publik adalah langkah yang bisa dilakukan. Pendidikan darurat adalah pilihan yang harus segera dipersiapkan, agar anak-anak tidak kehilangan ritme belajarnya.
Banjir yang melanda Bali bukan semata-mata murka alam. Curah hujan ekstrem memang menjadi pemicu, namun kerentanan infrastruktur dan lemahnya tata kelola lingkungan memperparah dampaknya. Drainase kota yang tersumbat sampah, sungai yang menyempit karena alih fungsi lahan, serta pembangunan yang kerap mengabaikan daya dukung lingkungan adalah faktor nyata yang memperbesar risiko banjir.
Dalam konteks pendidikan, kita harus bertanya: mengapa sekolah-sekolah bisa begitu mudah terendam? Apakah lokasi pembangunan sekolah selama ini memperhitungkan risiko bencana? Apakah ada standar infrastruktur pendidikan yang benar-benar tahan terhadap ancaman banjir, gempa, atau bencana lain? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, karena tanpa jawaban yang tegas, kita hanya akan mengulang tragedi serupa di masa depan.
Pemerintah pusat sudah menyinggung pentingnya memperkuat konsep Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Ini adalah langkah strategis yang harus dipercepat. SPAB tidak hanya soal membangun sekolah yang kokoh, tetapi juga menciptakan budaya kesiapsiagaan. Guru, murid, bahkan orang tua harus dibekali pemahaman bagaimana menghadapi bencana. Evakuasi harus menjadi keterampilan dasar. Kurikulum pendidikan bisa mengintegrasikan kesadaran lingkungan dan mitigasi bencana sejak dini.
Sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mendidik, tetapi juga melindungi. Di ruang kelas itulah generasi masa depan ditempa. Jika ruang itu rapuh, maka masa depan pun ikut rapuh.
Banjir jangan hanya direspons dengan duka dan janji perbaikan. Bencana harus menjadi momentum transformasi. Kita tidak boleh hanya membangun kembali sekolah-sekolah yang rusak dengan model lama, tetapi harus menghadirkan sekolah-sekolah yang benar-benar tangguh. Arsitektur bangunan harus menyesuaikan dengan kondisi geografis dan risiko bencana setempat. Sistem peringatan dini harus terkoneksi hingga ke sekolah-sekolah.
Selain itu, pembelajaran pascabencana harus mempertimbangkan aspek psikososial. Anak-anak yang baru saja kehilangan teman, keluarga, atau rumah, tentu tidak bisa langsung kembali belajar dengan kondisi normal. Trauma mereka harus diatasi. Guru perlu didukung agar mampu memberikan pendampingan emosional, bukan hanya materi akademik.
Banjir Bali kali ini adalah ujian kepemimpinan. Pemerintah daerah dituntut hadir bukan hanya dengan bantuan logistik, tetapi juga dengan kebijakan yang visioner. Publik tentu berharap agar para pemimpin daerah tidak berhenti pada seremoni kunjungan, melainkan benar-benar memastikan bahwa setiap anak bisa kembali ke ruang belajar dengan aman.
Masyarakat tidak bisa hanya menjadi penonton. Gotong royong menjaga kebersihan sungai, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut mengawasi pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif. Pendidikan anak-anak adalah kepentingan bersama, sehingga menjaga sekolah tetap aman dari bencana harus menjadi gerakan bersama.
Banjir telah mengajarkan bahwa pendidikan kita masih rapuh. Tetapi, di balik rapuh itu ada peluang untuk bangkit dengan lebih kuat. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja cepat, bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik. Anak-anak Bali berhak mendapatkan sekolah yang aman, guru yang siap siaga, dan lingkungan yang mendukung mereka untuk tumbuh tanpa dihantui ketakutan banjir.
Bali sering disebut sebagai pulau surga, tempat di mana harmoni antara manusia, alam, dan budaya dijaga. Banjir yang merusak sekolah-sekolah kita adalah tanda harmoni itu terganggu. Mari kembalikan harmoni itu. Karena masa depan Bali tidak hanya ditentukan oleh indahnya pantai dan megahnya pura, tetapi juga oleh seberapa teguh kita menjaga hak anak-anak untuk belajar, bahkan ketika banjir datang menghantam. (*)